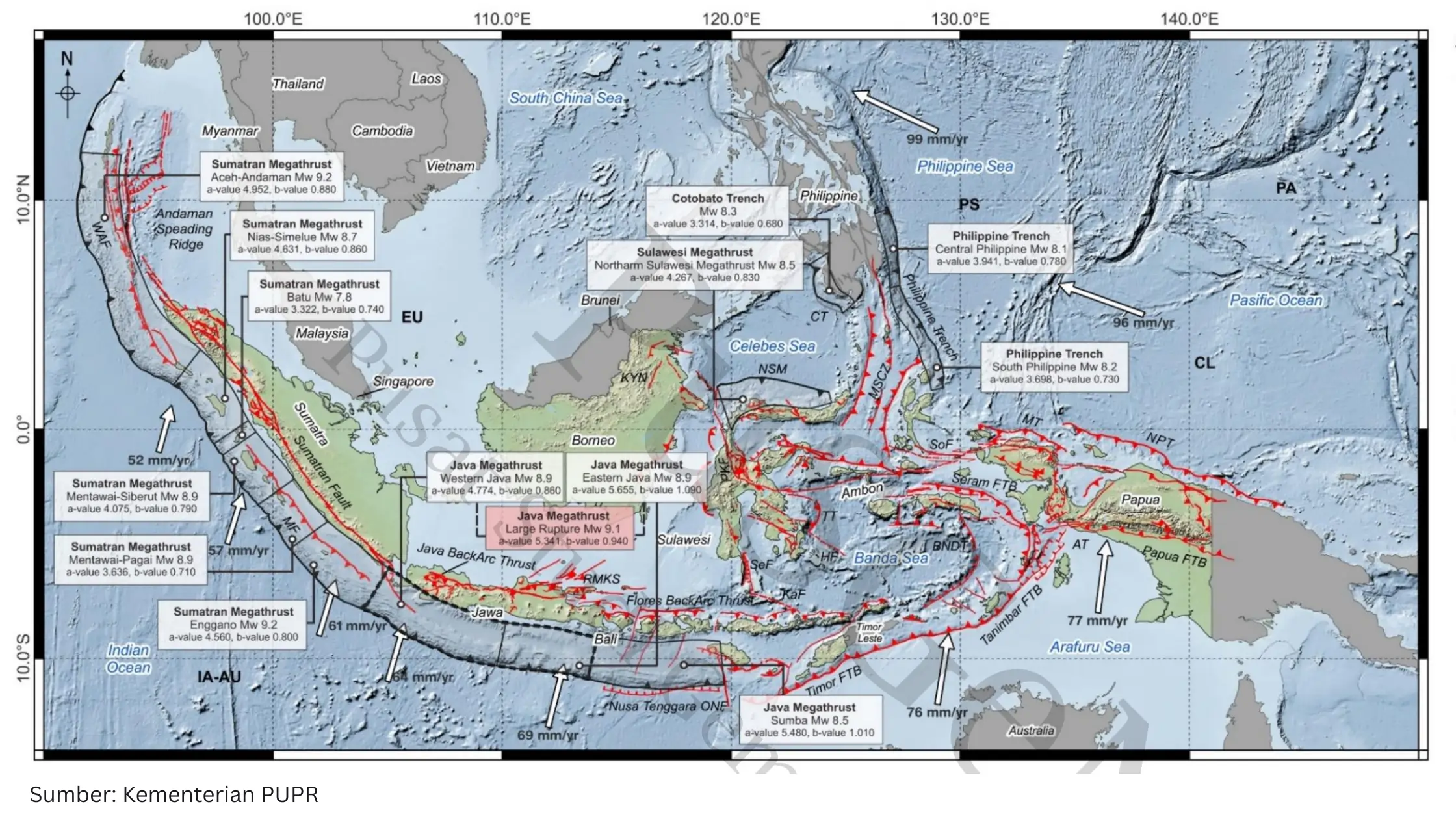Hujan deras yang turun tanpa jeda sejak akhir 24 November lalu menjelma menjadi rangkaian bencana yang memorak-porandakan empat kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam hitungan jam, banjir bandang dan longsor menghantam pemukiman, memutus akses, dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Skala peristiwa ini, menurut banyak warga, belum pernah mereka saksikan dalam puluhan tahun terakhir. Hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa alam tengah memberi peringatan keras.
Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, hingga 27 November 2025, sedikitnya 2.851 orang mengungsi dan 19 orang dilaporkan meninggal di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Basarnas belum menutup kemungkinan angka tersebut bertambah, mengingat proses evakuasi masih terus berlangsung di sejumlah lokasi terdampak.
BNPB menyebut bencana ini dipicu oleh pengaruh Siklon Tropis KOTO di Laut Sulu serta Bibit Siklon Tropis 95B (yang kemudian menjadi Siklon Tropis Senyar) di Selat Malaka, dua fenomena yang memicu hujan ekstrem dan angin kencang di wilayah Sumut. Namun, bagi organisasi lingkungan, penyebabnya tidak sesederhana itu. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara menegaskan bahwa kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia punya andil yang jauh lebih besar.
Baca juga: Dua Siklon Ini Disebut Penyebab Banjir Sibolga-Tapanuli, Apa Saja?
Akibat Kerusakan Ekologis
Dilansir dari Kompas.com, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menolak anggapan bahwa bencana itu murni disebabkan cuaca ekstrem. Ia menyebutkan bahwa ketika banjir terjadi, arus deras membawa banyak kayu, sementara citra satelit menunjukkan hutan di sekitar titik bencana telah lama gundul.
Bagi Jaka, bencana ini merupakan konsekuensi dari serangkaian keputusan politik yang mengorbankan keselamatan ekologis atas nama pembangunan. “Artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini,” ujar Jaka, Rabu, 26 November dilansir dari laman Walhi Sumut.
Menurut WALHI, kegagalan negara dalam mengelola lingkungan memperburuk krisis di Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), salah satu hutan tropis terakhir di Sumatera Utara yang meliputi tiga kabupaten: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Kawasan ini bukan hanya rumah bagi flora-fauna langka, termasuk orangutan tapanuli, melainkan juga benteng ekologis yang menentukan keselamatan masyarakat di sekitarnya.
WALHI menilai bencana di Sibolga dan Tapanuli adalah bencana ekologis. Mereka menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Batang Toru. Dari berbagai video yang beredar, terlihat banjir membawa material kayu dalam jumlah besar, yang oleh WALHI disebut sebagai bukti adanya aktivitas penebangan hutan di sekitar lokasi bencana.
Menurut laporan WALHI, salah satu perusahaan yang dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap kerusakan itu adalah Tambang Emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources (PT AR). Perusahaan ini menjalankan operasi melalui Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun, dengan wilayah konsesi yang berkembang pesat. Dari yang awalnya 6.560 km² pada 1997 menjadi 130.252 hektare yang membentang di empat kabupaten.