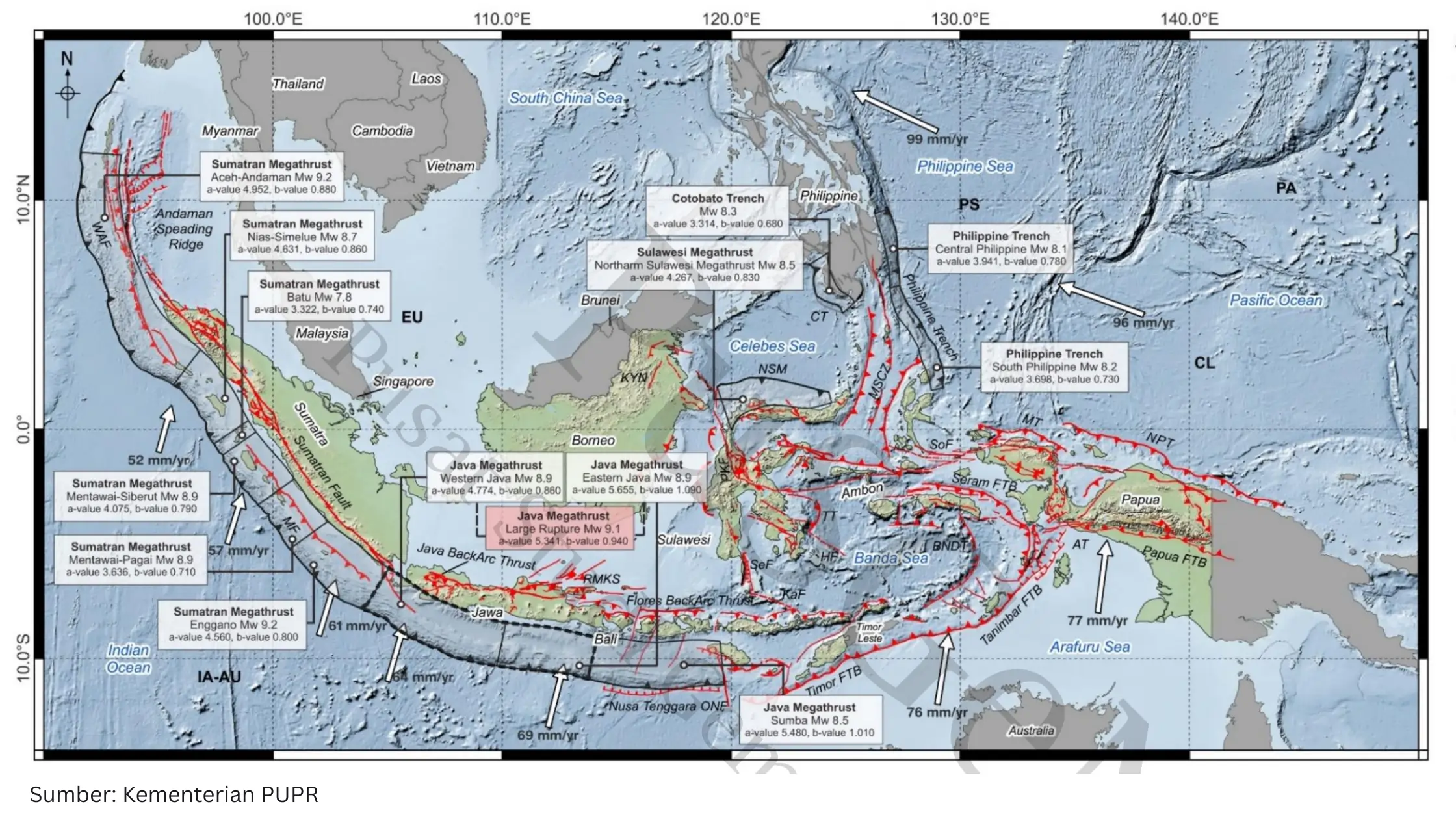Di tempat yang dulu berdiri warung Mak Wiwik dengan nasi uduknya yang legendaris, kini menjulang gerai waralaba asing berlampu terang. Mak Wiwik? Entah ke mana. Mungkin tersingkir ke gang sempit di pinggiran, atau mungkin sudah menyerah sama sekali. Inilah wajah gastrokolonialisme. Penjajahan model baru yang tidak lagi menggunakan meriam, melainkan melalui perut dan selera kita.
Gastrokolonialisme bukanlah istilah baru, tetapi dampaknya makin nyata di Indonesia. Ini adalah bentuk kolonialisme kontemporer saat makanan menjadi alat dominasi budaya dan ekonomi. Bedanya dengan kolonialisme klasik, kali ini kita yang rela membuka pintu lebar-lebar, bahkan menyambutnya dengan antusiasme.
Lihatlah bagaimana kota-kota besar kita bertransformasi. Sudut-sudut strategis dikuasai restoran cepat saji global. Mal-mal dipenuhi kafe bergaya Eropa. Aplikasi pesan-antar makanan didominasi menu fusion yang asing dari tradisi kita. Sementara itu, bagaimana dengan pedagang makanan lokal? Mereka dipinggirkan, dianggap tidak higienis, tidak modern, tidak instagramable. Mirisnya, ini bukan sekadar soal menu yang berubah. Ini soal bagaimana ruang hidup kita dirampas secara sistematis.
Pertanyaannya adalah siapa yang sesungguhnya mengatur apa yang kita makan dan bagaimana ruang-ruang kita ditata agar hanya jenis makanan tertentu yang mudah diakses?
Di sinilah konsep gastrokolonialisme menjadi relevan. Penjajahan melalui perut, melalui pangan, selera, dan ruang tempat makanan itu diproduksi, diperdagangkan, dan disantap. Sejumlah tulisan tentang gastrokolonialisme di Indonesia, termasuk laporan-laporan jurnalisme sejarah dan lingkungan, menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar menu makan siang, melainkan nasib komunitas, budaya, bahkan tata ruang negeri ini.
Kolonialisme yang Masuk Lewat Dapur
Kolonialisme klasik tidak hanya datang dengan meriam dan kapal dagang, tetapi juga dengan bibit tebu, kopi, dan pola tanam baru. Di banyak wilayah Nusantara, kolonialisme mengubah secara drastis hubungan orang dengan tanah dan makanan mereka sendiri.
Tanam paksa dan kebijakan perkebunan memaksa petani menanam komoditas ekspor: tebu, kopi, tembakau, karet. Lahan yang sebelumnya menumbuhkan pangan lokal seperti umbi-umbian, padi ladang, sagu, diubah menjadi hamparan monokultur. Tubuh tanah dipetakan ulang untuk memenuhi selera dan kebutuhan pasar dunia, bukan kebutuhan perut masyarakat setempat.
Di tingkat perut, dampaknya adalah keterputusan. Pangan yang dihasilkan dari tanah tempat mereka berpijak justru dikirim keluar. Di tingkat ruang, terbentuk pola baru. Desa-desa pada akhirnya bergantung pada satu komoditas dan berakibat pada terjadinya segregasi antara ruang produksi dan konsumsi.
Dari Tanam Paksa ke Hegemoni Beras dan Makanan Instan
Setelah kemerdekaan, bentuk penjajahan mungkin berubah, tetapi banyak logika lama yang bertahan. Negara mengejar swasembada beras, perusahaan benih dan pupuk global masuk lewat Revolusi Hijau, dan beras mengukuhkan diri sebagai satu-satunya simbol “pangan yang sesungguhnya”.
Akibatnya, pangan lokal, seperti sagu, jagung, jewawut, umbi-umbian, dan beragam biji-bijian tradisional, tersingkir ke pinggiran, baik secara budaya maupun secara spasial. Lahan-lahan yang masih tersisa dipadatkan menjadi sawah beririgasi teknis atau dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan perumahan.
Dalam beberapa dekade terakhir, muncul lapis baru, yaitu industri makanan ultra-proses dan jaringan ritel modern. Produk-produk pangan yang seragam, dari mi instan hingga camilan dalam kemasan, masuk hingga ke pelosok, sering kali lebih mudah diakses daripada bahan segar. Di banyak desa yang dikepung perkebunan besar, misalnya, masyarakat justru membeli makanan kemasan di kios karena lahan di sekitarnya ditanami sawit atau karet yang tidak bisa langsung dimakan.
Inilah gastrokolonialisme versi baru, Perut kita dikendalikan oleh perusahaan dan rantai pasok global, sementara ruang hidup kita ditata agar menguntungkan distribusi produk mereka.
Tata Ruang dan Gastrokolonialisme
Tata ruang sering dianggap urusan teknis, seperti peta, RTRW, IKN, kawasan industri, atau perumahan. Padahal, setiap garis di peta juga menentukan perjalanan sebuah bahan pangan dari tanah ke piring. Ia menentukan siapa yang punya akses ke tanah subur, pasar, dan meja makan.
Saat sawah di pinggir kota diganti menjadi klaster perumahan dan mal, misalnya, bukan hanya pemandangan yang berubah. Kita menciptakan kota yang harus bergantung pada pasokan pangan dari tempat yang makin jauh. Rantai pasok yang memanjang menguntungkan segelintir pemain besar dan mengunci kita pada sistem distribusi yang rapuh dan tidak adil.
Di dalam kota, tata ruang menentukan di mana pasar tradisional boleh berdiri, di mana pedagang kaki lima diizinkan atau digusur, dan di mana waralaba makanan cepat saji diberi ruang paling strategis. Kebijakan penataan kota yang mengusir pedagang kaki lima demi “keteraturan” pada dasarnya adalah kebijakan yang mengatur siapa boleh menjual makanan, di mana, dan kepada siapa. Itu adalah politik perut dalam bentuk paling nyata.
Kita menyebutnya penataan kota, tetapi ada bias kelas, rasa, dan kekuasaan di sana. Warung tegal dianggap “kumuh”, pasar basah dilabeli “kotor”, sementara restoran berpendingin udara dan gerai cepat saji di pusat perbelanjaan dianggap representasi “kota modern”. Ruang-ruang bersih, terang, teratur itulah yang diutamakan dalam peta tata ruang. Sementara, ruang kuliner rakyat diatur ulang, disembunyikan, atau digeser ke pinggir.
Kota-Kota yang Kehilangan Dapur Kolektifnya
Gastrokolonialisme juga menghancurkan cara komunitas mengorganisasi pangan secara sosial. Di banyak kampung, dulu, dapur bukan cuma ruang di belakang rumah, tetapi ruang sosial. Dapur menjadi tempat bertukar resep, menyiapkan makanan bersama saat panen atau upacara, berbagi hasil kebun, dan mentransfer pengetahuan kuliner lintas generasi.
Ketika tata ruang kota memecah kampung-kampung menjadi perumahan tertutup, apartemen, dan permukiman individualistik, dapur kolektif ini perlahan hilang. Ruang komunal menyusut, acara makan bersama tergantikan oleh layanan pesan-antar, dan relasi kita dengan makanan makin dimediasi oleh layar dan aplikasi.
Di satu sisi, kota kian dipenuhi restoran, kafe, dan gerai cepat saji. Di sisi lain, makin sedikit lahan bagi kebun komunitas, pasar rakyat, atau dapur umum yang bisa menopang kedaulatan pangan warga. Keseimbangan ini bergeser: kita membangun kota yang menyediakan banyak tempat untuk membeli makanan, tetapi sedikit sekali ruang untuk memproduksi dan mengolah makanan secara mandiri.
Tata ruang yang peka pangan (food-sensitive planning) pada dasarnya adalah upaya mengembalikan perut dan dapur warga ke pusat perencanaan. Ini cara praktis untuk melawan gastrokolonialisme dengan menjamin bahwa setiap kota dan desa punya ruang yang cukup untuk menanam, mengolah, dan menjual pangan yang berakar pada budaya dan ekologi setempat.