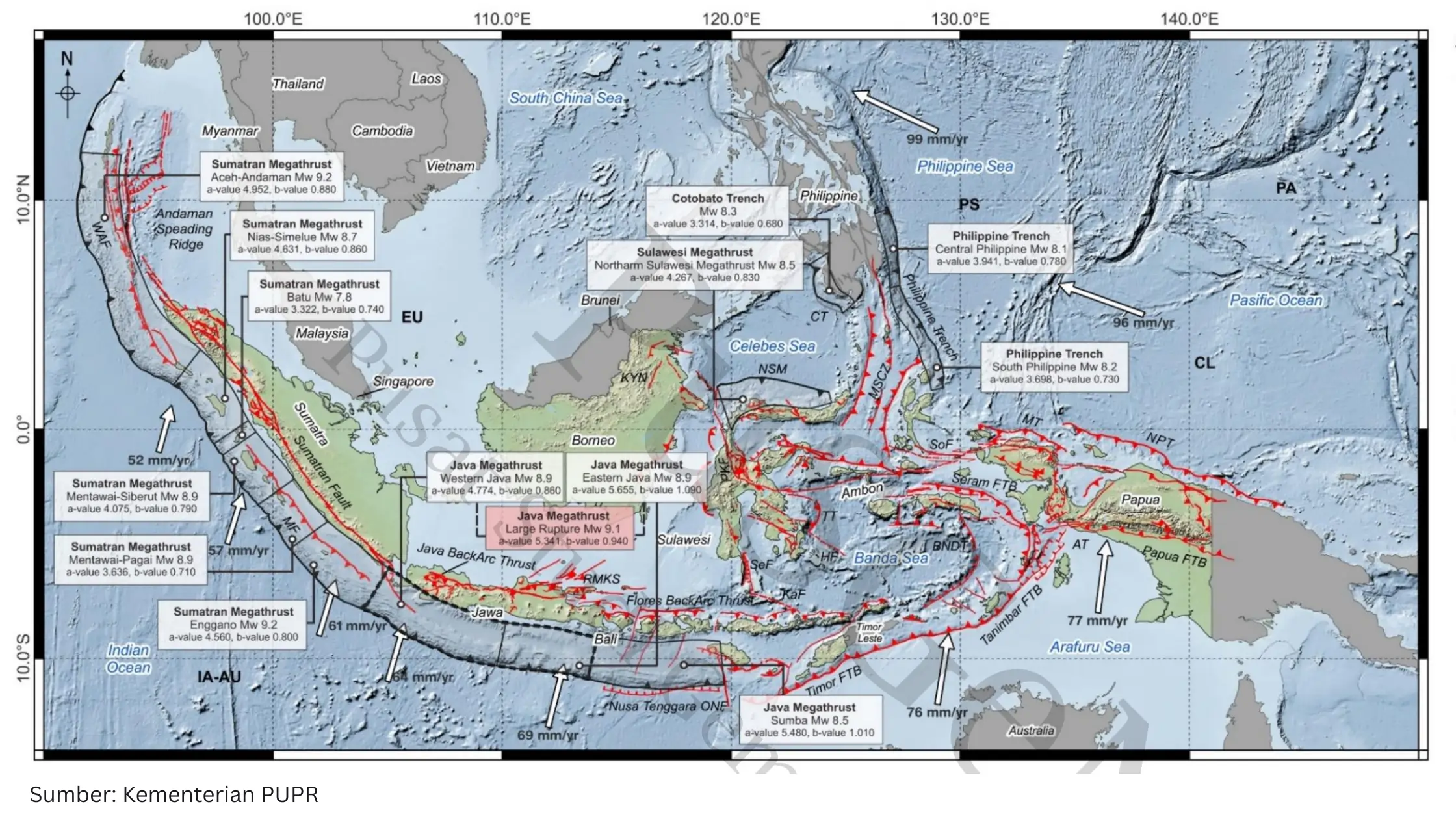Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode terberat dalam sejarah kebencanaan Indonesia, khususnya bencana hidrometeorologi. Sejak Januari hingga pertengahan Desember, banjir terjadi hampir tanpa jeda dan tersebar merata dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Berdasarkan data Geoportal Data Bencana Indonesia per 23 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.608 kejadian banjir di seluruh wilayah nasional. Secara spasial, sebaran kejadian ini memperlihatkan konsentrasi tinggi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, wilayah dengan kepadatan penduduk, tekanan pembangunan, serta degradasi lingkungan yang signifikan. Fakta ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi peristiwa musiman, melainkan fenomena berulang yang mengikuti pola kerentanan ruang dan pengelolaan wilayah.
Banjir mendominasi hampir 70 persen dari total kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2025, disusul oleh 688 kasus cuaca ekstrem, 230 kejadian tanah longsor, serta 546 peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Dominasi ini menunjukkan bahwa persoalan tata ruang yang tidak terkendali, kerusakan ekosistem, dan dampak perubahan iklim telah berkelindan menjadi krisis struktural yang saling memperkuat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa pembenahan tata ruang dan pengelolaan lingkungan berbasis data geospasial yang kuat, apakah banjir akan menjadi pola tahunan yang makin normal dan diterima sebagai takdir oleh masyarakat Indonesia?
Cuaca Ekstrem atau Faktor Kerusakan Lingkungan?
Sepanjang tahun 2025, Indonesia menghadapi rangkaian banjir yang memunculkan pertanyaan mendasar, apakah bencana ini semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem, atau justru merupakan cerminan dari degradasi lingkungan yang kian parah dan terakumulasi selama bertahun-tahun? Namun nyatanya, banjir tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan tekanan lingkungan dan tata ruang yang tinggi. Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi muncul sebagai episentrum banjir nasional, memperlihatkan keterkaitan erat antara kondisi biofisik wilayah dan aktivitas manusia dalam memperbesar risiko bencana.
Pulau Jawa menjadi kawasan paling rentan karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta intensitas pembangunan yang masif, terutama di dataran banjir sungai-sungai besar. Alih fungsi lahan yang masif dari kawasan resapan menjadi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.
Hal tersebut terlihat jelas pada banjir yang terjadi di Kabupaten Kendal. Grobogan, dan Batang. Wilayah tersebut terkena dampak paling parah karena secara spasial berada di bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) besar yang telah lama mengalami tekanan akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai. Kondisi ini mencapai titik kritis ketika tanggul sungai di Grobogan jebol, merendam ribuan rumah warga sekaligus memutus jalur kereta api utama. Akibatnya, hujan dengan intensitas tinggi sedikit saja sudah cukup untuk memicu limpasan permukaan dan banjir luas. Di sisi lain, kapasitas sungai yang menyempit akibat sedimentasi dan pembangunan di sempadan sungai makin memperparah risiko genangan di wilayah hilir.
Sumatera menghadapi persoalan yang berbeda namun saling berkaitan, yakni kerusakan hutan di wilayah hulu DAS yang berpadu dengan curah hujan ekstrem. Deforestasi dan degradasi hutan menghilangkan fungsi alami hutan sebagai pengatur tata air sehingga hujan lebat dengan cepat berubah menjadi banjir bandang dan longsor. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS dari UGM, yang menegaskan bahwa rangkaian bencana akhir November 2025 di Sumatera merupakan bagian dari pola berulang.
Hatma menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) telah menghilangkan fungsi dasar kawasan hutan sebagai pengendali daur air. Tanpa tutupan hutan, proses intersepsi, infiltrasi, hingga evapotranspirasi melemah drastis sehingga menyebabkan erosi dan limpasan permukaan menjadi tak terkendali. Ia menegaskan bahwa hutan alami bekerja bak spons raksasa yang menyerap air hujan.
Sementara itu, Sulawesi menunjukkan kerentanan khas wilayah kepulauan, di mana kawasan pesisir dan dataran rendah makin tertekan oleh alih fungsi lahan, reklamasi, dan ekspansi permukiman. Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menyebutkan bahwa berdasarkan data tahun 2019 luas sawah Maros tercatat 26.205 hektar. Setelah pembaruan LBS tahun 2024, tersisa 25.276 hektar. Berarti sekitar 1.700 hektar telah beralih fungsi. Ia menjelaskan, alih fungsi terbesar terjadi di kawasan pengembangan perkotaan.
Kombinasi faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa banjir di Indonesia telah bertransformasi dari bencana lokal menjadi fenomena regional yang mengikuti karakter DAS, topografi, serta pola penggunaan lahan. Tanpa pembenahan serius terhadap pengelolaan lingkungan dan tata ruang berbasis data geospasial, banjir berpotensi menjadi pola tahunan yang makin sulit dikendalikan.
Apa yang Harus Kita Lakukan?
Pola banjir sepanjang 2025 memberi pelajaran penting tentang apa yang bisa kita lakukan ke depan. Bencana yang terjadi menunjukkan dua gambaran besar. Pertama, banjir di kawasan perkotaan yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, ekonomi, hingga layanan publik. Kedua, banjir di wilayah pedesaan yang dipicu oleh rusaknya lingkungan di bagian hulu sungai. Di kota-kota besar, masalah utama berasal dari pembangunan yang terlalu padat, berkurangnya lahan resapan air, serta sungai yang menyempit akibat bangunan dan sampah. Sementara di wilayah pedesaan, terutama di kawasan pegunungan dan hulu sungai, kerusakan hutan membuat air hujan tidak lagi tertahan secara alami.
Hutan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur air. Pepohonan dan tanah hutan mampu menahan air hujan, menyerapnya ke dalam tanah, lalu melepaskannya sedikit demi sedikit ke sungai. Ketika hutan ditebang atau dialihfungsikan, kemampuan ini hilang. Air hujan langsung mengalir di permukaan tanah, membawa lumpur dan pasir, lalu menyebabkan banjir dan longsor di wilayah hilir. Oleh karena itu, hutan sering diibaratkan seperti spons besar yang menyerap air. Jika spons ini rusak, air akan langsung tumpah dan menimbulkan bencana.
Untuk mencegah banjir terus berulang, pemerintah perlu menggunakan data yang akurat dan mudah dipahami, terutama data berbasis peta. Peta aliran sungai, kondisi hutan, ketinggian wilayah, dan jumlah penduduk bisa membantu menentukan daerah mana yang rawan banjir dan perlu perhatian khusus. Dengan data ini, perencanaan pembangunan bisa lebih hati-hati dan tidak merusak lingkungan. Jika tata ruang terus disusun tanpa mempertimbangkan kondisi alam, banjir akan menjadi masalah tahunan yang makin merugikan masyarakat dan mengancam masa depan lingkungan Indonesia.
Ke depan, hidup berdampingan dengan bencana bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan belajar beradaptasi secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan data yang ada. Dengan perencanaan berbasis informasi yang akurat, teknologi geospasial, serta kepedulian bersama terhadap lingkungan, pola-pola bencana yang berulang dapat ditekan, risiko dapat dikurangi, dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.