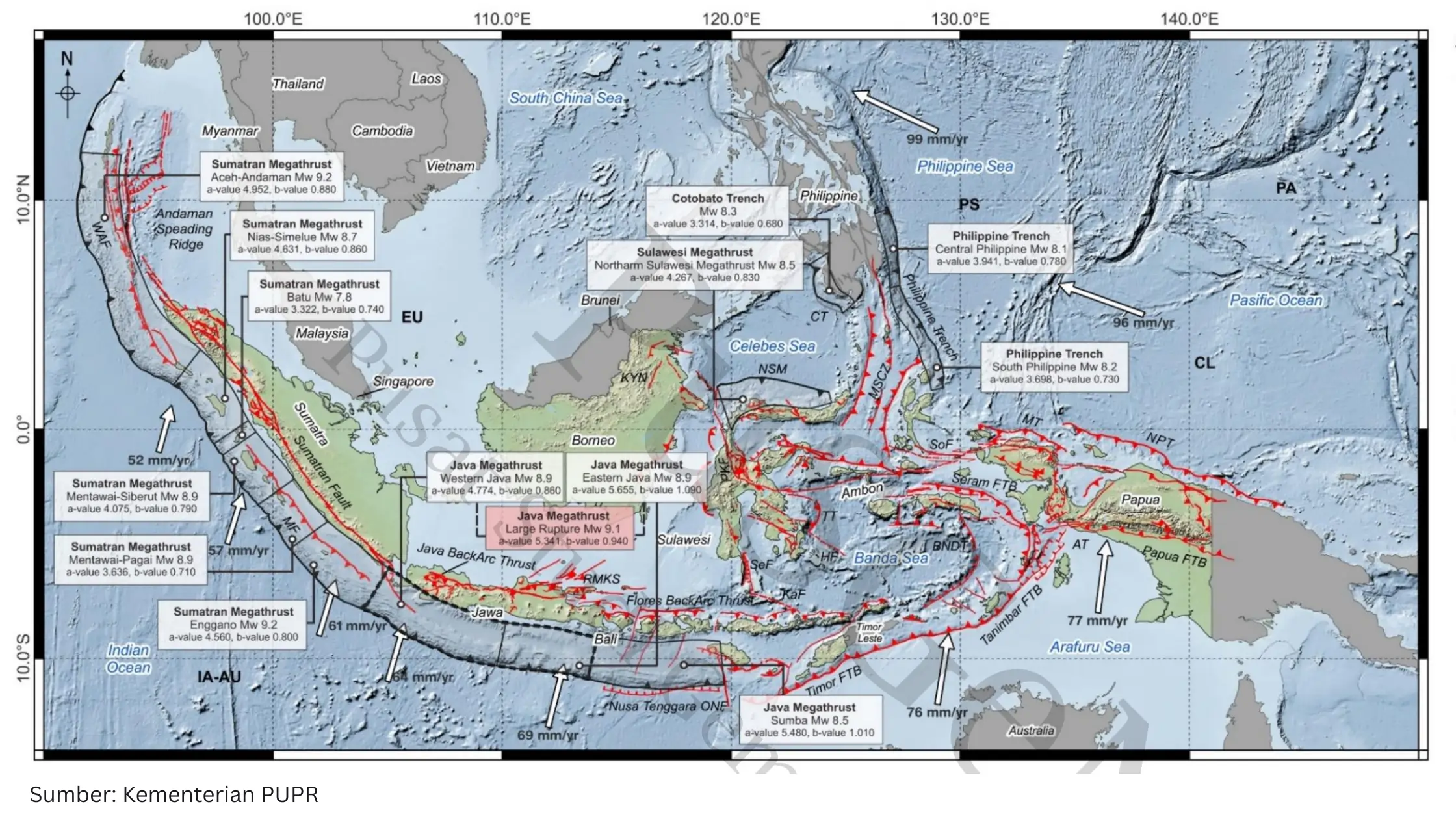Banjir bandang yang menerjang Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada September 2025 menjadi sorotan serius. Peristiwa ini dianggap tidak biasa karena terjadi di tengah musim kemarau. Menurut laporan BMKG, banjir tersebut dipicu oleh hujan ekstrem dengan intensitas lebih dari 300 milimeter hanya dalam waktu sehari. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan tata ruang, infrastruktur, dan ketangguhan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi.
Guru Besar Geomorfologi Lingkungan Fakultas Geografi UGM, Prof. Djati Mardiatno, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Indonesia sudah memasuki masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju penghujan. Ia menilai banjir bandang di Bali dan NTT muncul akibat kombinasi curah hujan ekstrem dengan berkurangnya tutupan lahan.
“Berkurangnya hutan yang berubah menjadi area terbangun membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan daripada masuk ke dalam tanah. Aliran permukaan yang besar inilah yang dapat memicu banjir bandang,” jelasnya pada Rabu, 17 September 2025, dikutip dari laman resmi UGM.
Djati menambahkan, luasnya wilayah terdampak serta banyaknya objek vital di kawasan perkotaan menjadi tantangan terbesar dalam penanganan banjir bandang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang berupa penataan tata ruang. “Kita harus memperbanyak ruang terbuka hijau agar air hujan bisa meresap ke tanah, membatasi konversi lahan hutan, serta memastikan sungai tidak tersumbat sampah agar saluran air berfungsi optimal,” tegasnya.
Pandangan senada datang dari Prof. Bakti Setiawan, pakar perencanaan kota dari Fakultas Teknik UGM. Menurutnya, banjir tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat ulah manusia.
“Ada faktor eksternal berupa perubahan iklim, tetapi ada juga faktor internal, yaitu tata ruang dan perkembangan kota yang tidak terkontrol. Jadi, tantangan utamanya adalah penataan ruang dan kota yang lemah dalam mengantisipasi risiko bencana,” ujarnya.
Bakti menilai bahwa solusi ke depan harus menekankan pengendalian tata ruang dan pertumbuhan kota yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas komunitas. “Peningkatan ketangguhan warga melalui penguatan social capital, baik secara struktural maupun kultural, perlu dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” imbuhnya.
Kedua akademisi tersebut sepakat bahwa menghadapi cuaca ekstrem membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia akademik, dan masyarakat. Pemerintah daerah harus menyiapkan rencana kontingensi sekaligus menegakkan aturan tata ruang. Akademisi dapat berperan lewat riset, pemetaan, dan edukasi publik.
Sementara itu, masyarakat diharapkan aktif meningkatkan kesiapsiagaan melalui langkah sederhana. Contohnya, masyarakat bisa membuat sumur resapan dan biopori, menjaga ruang terbuka hijau, hingga disiplin tidak membuang sampah ke sungai.