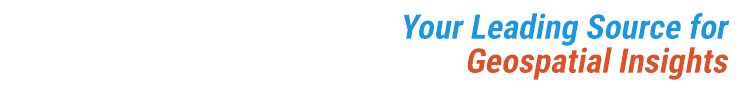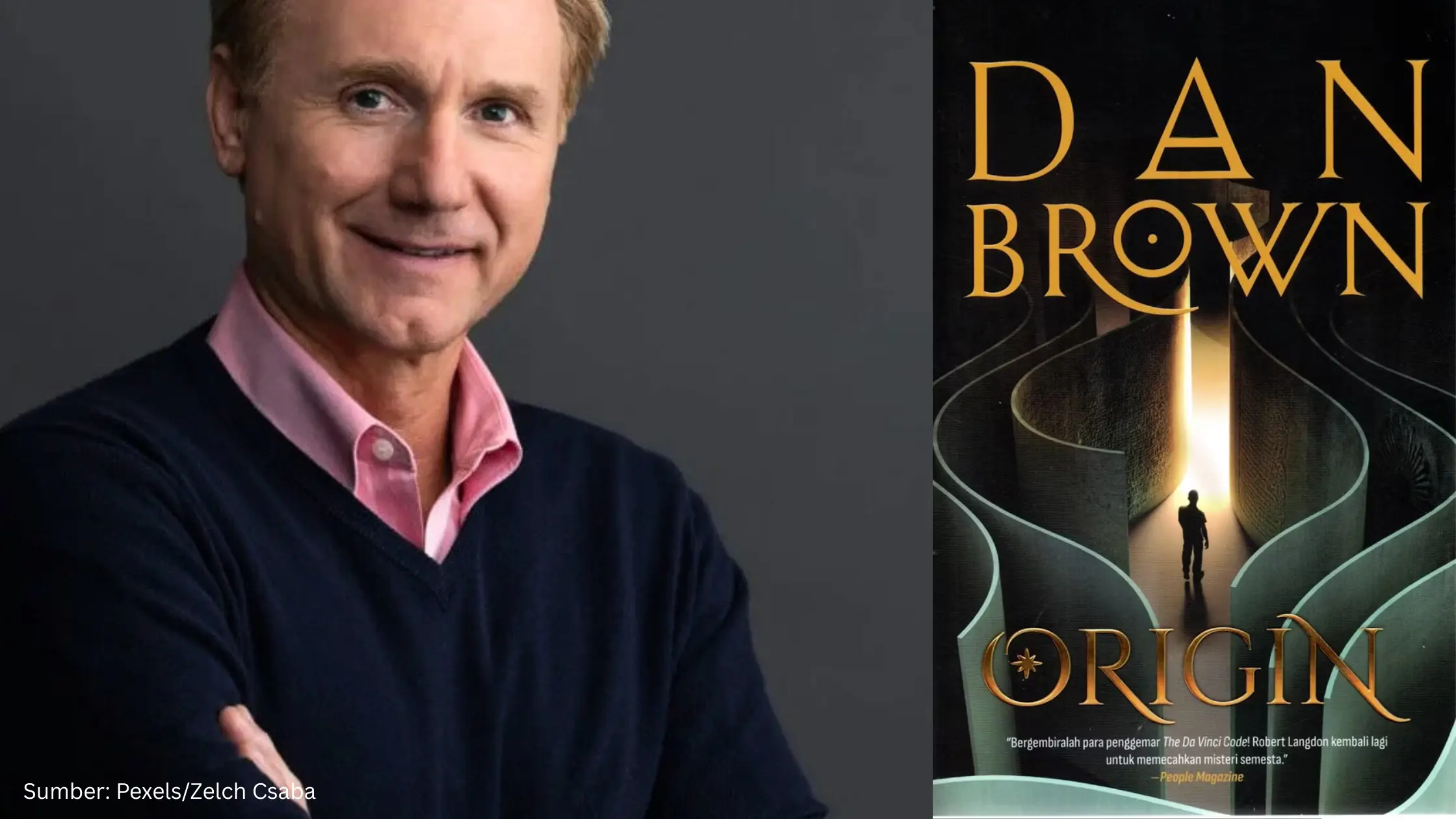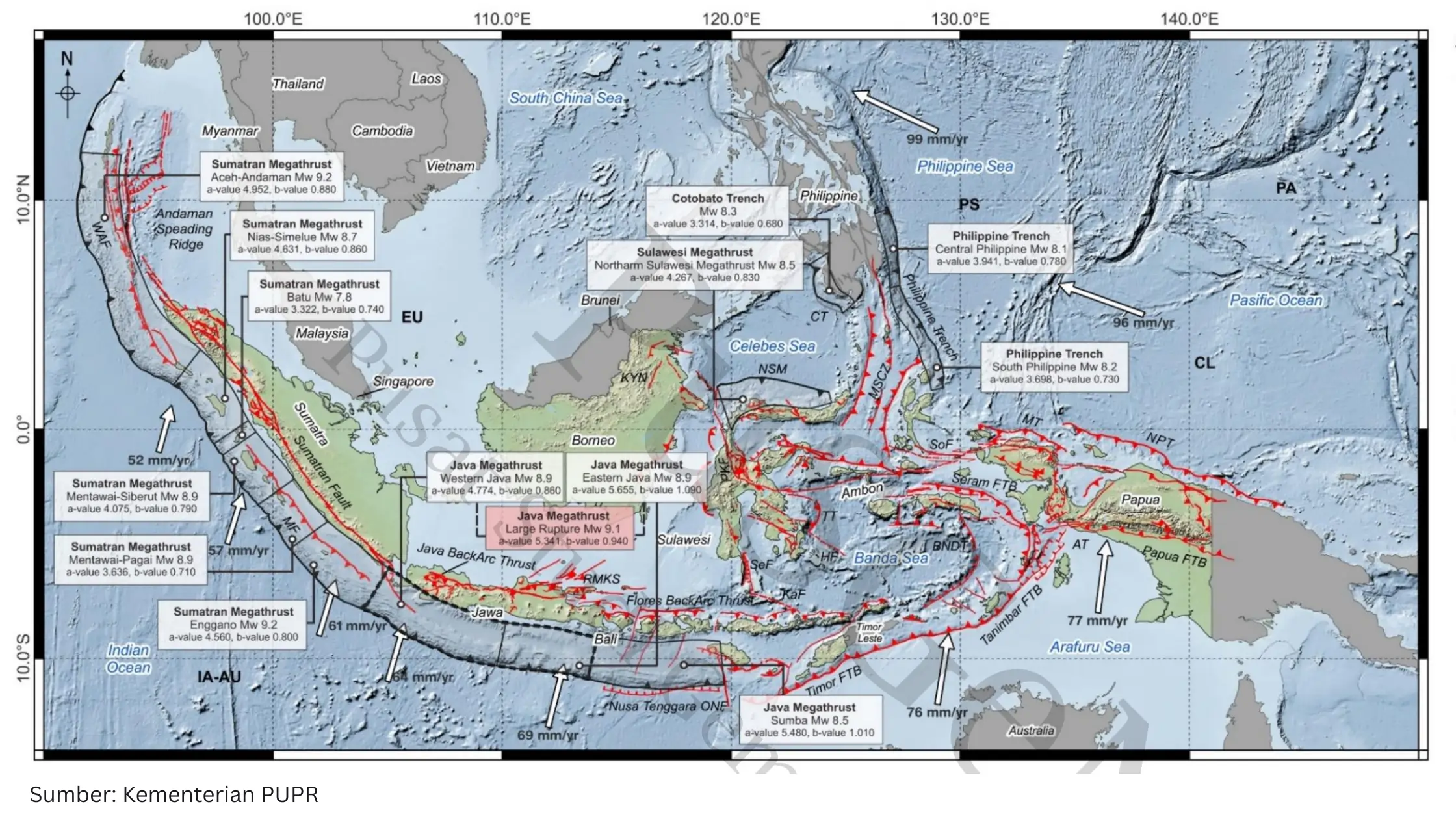Pulau Bali, yang selama ini identik dengan keindahan alam, ketenangan spiritual, dan destinasi wisata kelas dunia, mendadak berubah muram pada Rabu, 10 September 2025. Hujan deras semalaman menjelma menjadi banjir besar yang melumpuhkan aktivitas warga, merendam permukiman, dan merenggut korban jiwa. Dari Jembrana hingga Denpasar, aliran air bah menerjang tanpa kompromi, meninggalkan jejak kehancuran di tengah lanskap yang selama ini dikenal memesona. Jalan-jalan utama terputus, rumah-rumah warga tak berdaya di bawah genangan, hingga fasilitas publik lumpuh seketika.
Data resmi dari ANTARA mencatat, hujan yang mengguyur sejak Selasa malam, 9 September 2025 memicu banjir parah yang masih berlangsung hingga Rabu pagi. Di Jembrana, dua orang terseret arus deras dan kehilangan nyawa. Sementara di Denpasar, sebuah ruko ambruk diterjang banjir, merenggut empat korban jiwa sekaligus. Hingga Rabu petang, korban meninggal dunia mencapai sembilan orang, dengan dua orang dilaporkan hilang. Lebih dari 620 jiwa, atau 202 kepala keluarga, terpaksa mengungsi setelah enam kabupaten/kota, yaitu Denpasar, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, dan Tabanan, terdampak banjir besar. Situasi ini dengan cepat memaksa pemerintah menetapkan status darurat bencana.
Namun, bencana ini seakan menyisakan pertanyaan mendasar, mengapa banjir sebesar ini bisa terjadi di Bali? Apakah semua ini semata karena cuaca ekstrem yang datang tiba-tiba, atau justru ada faktor lain yang lebih dalam, yakni rapuhnya tata ruang dan maraknya alih fungsi lahan di Pulau Dewata?
Jejak Banjir Besar di Bali
Banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025 tercatat sebagai yang terparah dalam beberapa dekade terakhir. Peristiwa ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian bencana banjir besar yang beberapa kali menghantam Pulau Dewata.
Dilansir dari akun X @zakiberkata, pada Januari 2009, hujan deras yang berlangsung lebih dari delapan jam menyebabkan sekitar 2.000 rumah terendam. Wilayah yang paling parah terdampak saat itu adalah Denpasar, Gianyar, dan Badung. Dua tahun kemudian, Februari 2011, giliran Buleleng yang diterjang bencana. Di Kecamatan Gerokgak, sebanyak 475 rumah terendam, sejumlah titik mengalami longsor, bahkan satu sekolah dilaporkan hancur.
Rentetan bencana berlanjut pada Juli 2023. Hampir seluruh wilayah Bali, mulai dari Badung, Bangli, Denpasar, Jembrana, Karangasem, Gianyar, Klungkung, hingga Tabanan, mengalami banjir disertai tanah longsor. Catatan resmi ICFM menyebutkan sedikitnya lima orang tewas dan satu lainnya hilang akibat bencana tersebut.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa banjir di Bali bukanlah anomali baru, melainkan fenomena berulang yang makin sering terjadi dan kian mematikan. Banjir 2025 hanya menjadi puncak dari persoalan lama yang belum kunjung ditangani secara serius.
Gelombang Rossby dan Curah Hujan Ekstrem
Dikutip dari Kompas, Kepala BMKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, memaparkan bahwa dalam dua hari terakhir intensitas hujan di Bali berada pada kategori lebat dengan curah di atas 50 mm per hari, bahkan mencapai level ekstrem di atas 150 mm per hari. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby yang mendorong pertumbuhan awan konvektif. Ditambah lagi, kelembaban udara hingga ketinggian 200 mb atau sekitar 12.000 meter mendukung pembentukan awan tinggi yang kemudian menghasilkan hujan deras disertai kilat dan petir. BMKG juga mengingatkan bahwa potensi hujan ekstrem masih berpeluang terjadi di Bali dalam tiga hari mendatang.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa banjir besar kali ini tidak bisa dipandang sekadar peristiwa lokal semata. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara dinamika atmosfer global, kondisi kelembaban tropis, dan faktor meteorologi regional yang bersama-sama memicu hujan ekstrem sekaligus banjir kilat.
Air Bah di Atas Lahan yang Telanjur Terbangun
Selain faktor iklim, penyebab banjir besar di Bali tak lepas dari ulah manusia sendiri. Faktor antropogenik, terutama maraknya alih fungsi lahan, memainkan peran penting dalam memperparah bencana ini. Studi Ramadhan & Murti pada tahun 2024 yang berjudul “Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan” mencatat bahwa dalam kurun 2018–2023, kawasan Metropolitan Sarbagita, yang mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, kehilangan lahan sawah dalam jumlah signifikan. Denpasar menyusut 784 hektare, Badung 1.099 hektare, Gianyar 1.276 hektare, dan Tabanan 2.676 hektare. Totalnya, lebih dari 6.800 hektare sawah lenyap berganti menjadi kawasan terbangun.
Hilangnya area resapan ini makin mengkhawatirkan karena terjadi justru di sekitar pusat-pusat pariwisata utama, seperti Sanur, Kuta, Ubud, dan Tanah Lot. Padahal, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis vital alami untuk menyerap limpasan air hujan. Ketika lahan resapan berubah menjadi hotel, vila, maupun area komersial, maka air hujan yang seharusnya meresap ke tanah kini mengalir deras ke permukiman dan sungai, menciptakan risiko banjir yang jauh lebih tinggi.
Senada dengan penelitian tersebut, dilansir dari Kompas, pakar tata ruang Universitas Warmadewa, Nyoman Gede Maha Putra, menegaskan bahwa berkurangnya sawah, tegalan, dan hutan telah merampas kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, seluruh air permukaan mengalir deras ke sungai tanpa peredaman alami. Ia juga menyoroti hilangnya daerah sempadan sungai yang dulu berfungsi sebagai zona limpasan banjir. Menurutnya, kondisi ini menjadi peringatan keras untuk meninjau ulang tata ruang kota Bali yang kini makin sesak oleh bangunan.
Pernyataan tersebut sejatinya adalah alarm bahwa tata ruang tidak boleh hanya dipahami sebagai “tata uang” atau sekadar instrumen ekonomi dan investasi. Ia harus kembali pada fungsinya sebagai instrumen keberlanjutan, yaitu menjaga ruang resap air, melindungi ekosistem, dan memastikan pembangunan tidak menciptakan bencana baru. Tanpa tata ruang yang tepat, Pulau Dewata akan terus menanggung risiko yang kian besar setiap kali hujan ekstrem datang.
Saatnya Menata Ulang Tata Ruang yang Serampangan
Banjir besar yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 sejatinya lahir dari gabungan dua faktor, fenomena alam dan campur tangan manusia. Dari sisi alam, hujan ekstrem akibat gelombang Rossby memicu pertumbuhan awan tebal yang menurunkan curah hujan sangat tinggi. Namun, yang membuat dampaknya makin parah adalah ulah manusia melalui alih fungsi lahan dan pembangunan tanpa kendali. Sawah, hutan, dan tegalan yang dulu berfungsi sebagai area resapan kini hilang, berganti menjadi hotel, vila, atau permukiman. Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap justru mengalir deras ke permukaan, memenuhi sungai, dan berakhir dengan banjir besar yang melumpuhkan berbagai wilayah di Bali.
Peristiwa ini memberi pelajaran penting bahwa banjir bukan hanya bencana alam, melainkan juga cermin kegagalan tata ruang. Jika lahan resapan terus dikorbankan demi kepentingan pembangunan jangka pendek, Bali akan selalu rentan terhadap bencana serupa. Oleh karena itu, arah pembangunan perlu segera ditata ulang dengan memperluas zona lindung, mengembalikan fungsi lahan resapan, serta memastikan izin pembangunan benar-benar sesuai dengan rencana tata ruang digital (RDTR) yang terintegrasi. Tanpa langkah tegas, setiap hujan lebat di masa depan berpotensi kembali menjadi tragedi.