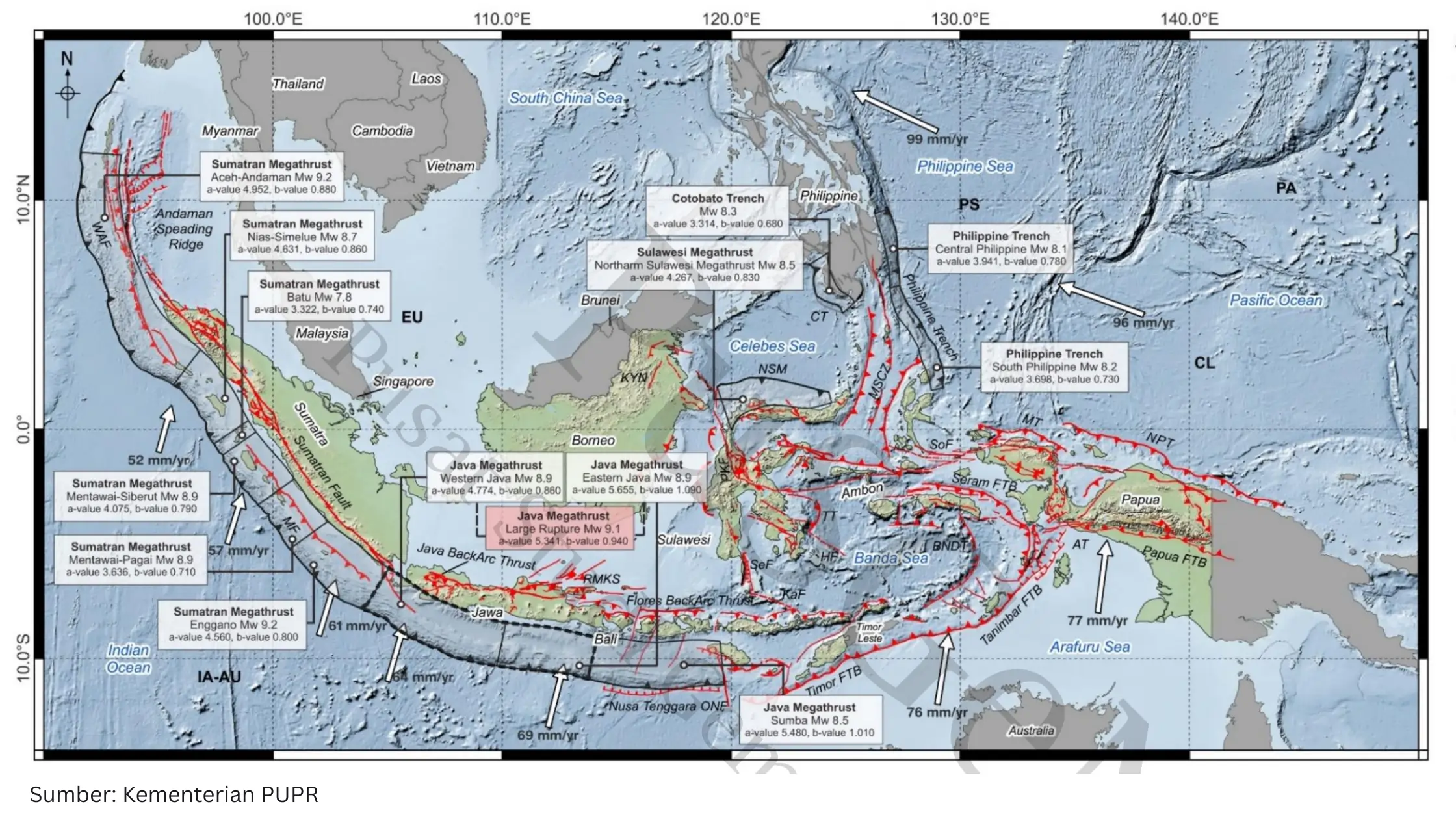Di tengah derasnya tuntutan keberlanjutan dan meningkatnya konflik agraria, industri tambang dan kehutanan memasuki babak baru yang menuntut pendekatan lebih sensitif terhadap ruang dan masyarakat. Dalam seminar “Meramu Keberlanjutan Teknik Geodesi: Hilirisasi dan Inovasi Informasi Lokasi dengan Keteknikan Geospasial”, Mokhamad Zaim Nurhidayat, S.T., Head of Land Management PT Vale Indonesia Tbk, tampil dengan satu istilah yang langsung menangkap perhatian, yaitu eco-sociospatial.
Bagi Zaim, konsep ini bukan sekadar istilah akademik. Ia adalah cara berpikir baru tentang bagaimana ruang dipetakan dan dikelola. “Eco-sociospatial itu analoginya adalah bagaimana kita menata ruang dari hasil produk geodesi, kemudian bermanfaat berkesinambungan untuk ekosistem dan sosial,” ujarnya di Fakultas Teknik, UGM, Jumat, 28 November 2025.
Zaim tidak menutupi bahwa dua industri besar, mineral dan kehutanan, masih “struggling” menghadapi persoalan residu dan konflik lahan yang panjang. Meski tambang hanya menempati sekitar 5 persen daratan Indonesia, konflik yang muncul tak kalah besar dibanding wilayah hutan yang mencapai 51 persen daratan.
Saat yang sama, kedua industri ini sedang mengalami pergeseran besar menuju perdagangan karbon. Ia mencatat bahwa perusahaan tambang kini menyimpan Rp30–35 triliun sebagai jaminan reklamasi untuk penutupan tambang. “Itu angka yang luar biasa besar, dan menunjukkan betapa seriusnya tuntutan keberlanjutan dalam industri tambang,” kata Zaim.
Di sisi lain, industri kehutanan mulai bergerak menjadi penyedia karbon terserap. Potensi ekonominya juga tak kecil. “Potensinya bisa mencapai 41 triliun per tahun. Ini peluang besar kalau kita hilirisasi,” ujarnya.
Pekerjaan Geospasial yang Tidak Pernah Bisa Dilepaskan
Perdagangan karbon bukan sekadar soal hitungan ekonomi. Ia membutuhkan kepastian ilmiah, dan itu berarti peta, citra satelit, survei lapangan, hingga model spasial. “Semua metodologi karbon, seperti VERRA atau Gold Standard, mensyaratkan menghitung stok karbon berbasis geospasial,” ujar Zaim. Dalam industri karbon, perhitungan carbon stock adalah inti, dan geospasial menjadi fondasinya.
Hal serupa terjadi pada industri tambang. Standar internasional, seperti Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), mengharuskan perusahaan memiliki rencana penutupan tambang yang memadai dan berbasis data spasial. “Di situ diperlukan sekian tenaga geospasial dengan sekian kompetensinya. Ini nanti kompetensi-kompetensi saling berkolaborasi,” jelasnya.
Soal Pembebasan Lahan
Jika ada isu yang paling rumit dalam industri ekstraktif, pembebasan lahan adalah salah satunya. Di ranah internasional, standar seperti IFC, IRMA, dan ICMM menetapkan aturan ketat mengenai resettlement. “IFC itu mensyaratkan resettlement dengan segala pernak-perniknya, termasuk pengukuran, database orang yang dibebaskan lahannya. Semua itu harus di-maintain,” terang Zaim.
Zaim menjelaskan bahwa resettlement terbagi menjadi dua bentuk: physical displacement dan economical displacement. Indonesia pernah mengenal proses ini melalui LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Menurut Zaim, LARAP bukan sekadar dokumen teknis, melainkan juga pekerjaan geospasial yang menentukan nasib hidup seseorang.
“Kalau rumah seorang warga dibebaskan, dia pindah. Tapi dampak mata pencahariannya bagaimana? Kalau awalnya petani, lalu lahan dipakai tambang, dia harus pindah dan itu di-manage. Itu sudah geospasial,” contoh Zaim.
Setiap perpindahan manusia membawa implikasi ekologi dan sosial. Semua itu dianalisis melalui EGIS. Hal itu memperlihatkan bagaimana peta adalah cermin perubahan hidup seseorang.
Transisi Karbon dan Peran Besar Industri Kehutanan
Indonesia memiliki target besar dalam NDC 2030, yaitu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Hutan menjadi penopang utamanya. “Sektor hutan memegang peran paling besar dalam pelaksanaan penurunan emisi karbon di Indonesia,” tegas Zaim.
Dalam perdagangan karbon domestik, setiap industri diberi ambang batas emisi. Jika melampaui batas, mereka wajib membeli kredit karbon dari sektor lain, umumnya kehutanan. Proyek karbon apa pun bentuknya, dari REDD+ hingga restorasi hutan, semuanya membutuhkan pemetaan detail, seperti batas area, potensi stok karbon, hingga desain aksi mitigasi.
“Stok di Indonesia belum tentu menjadi nilai jual. Harus ada satu aksi mitigasi, dan itu di-support teman-teman geospasial. Kalau di hutan, ya penanaman dan pengelolaannya. Kata 'di mana' itu kan aspek geodesi,” jelasnya.
Bagi Zaim, eco-sociospatial adalah jawaban atas banyak keruwetan industri ekstraktif hari ini. Ia menjadi jembatan antara ruang, ekosistem, dan manusia, tiga hal yang sering kali tidak disatukan dalam pengelolaan industri. “Kenapa eco-sociospatial? Karena untuk mengelola tambang dan kehutanan, kita perlu pendekatan yang berbasis keberlanjutan di masyarakat,” terangnya.