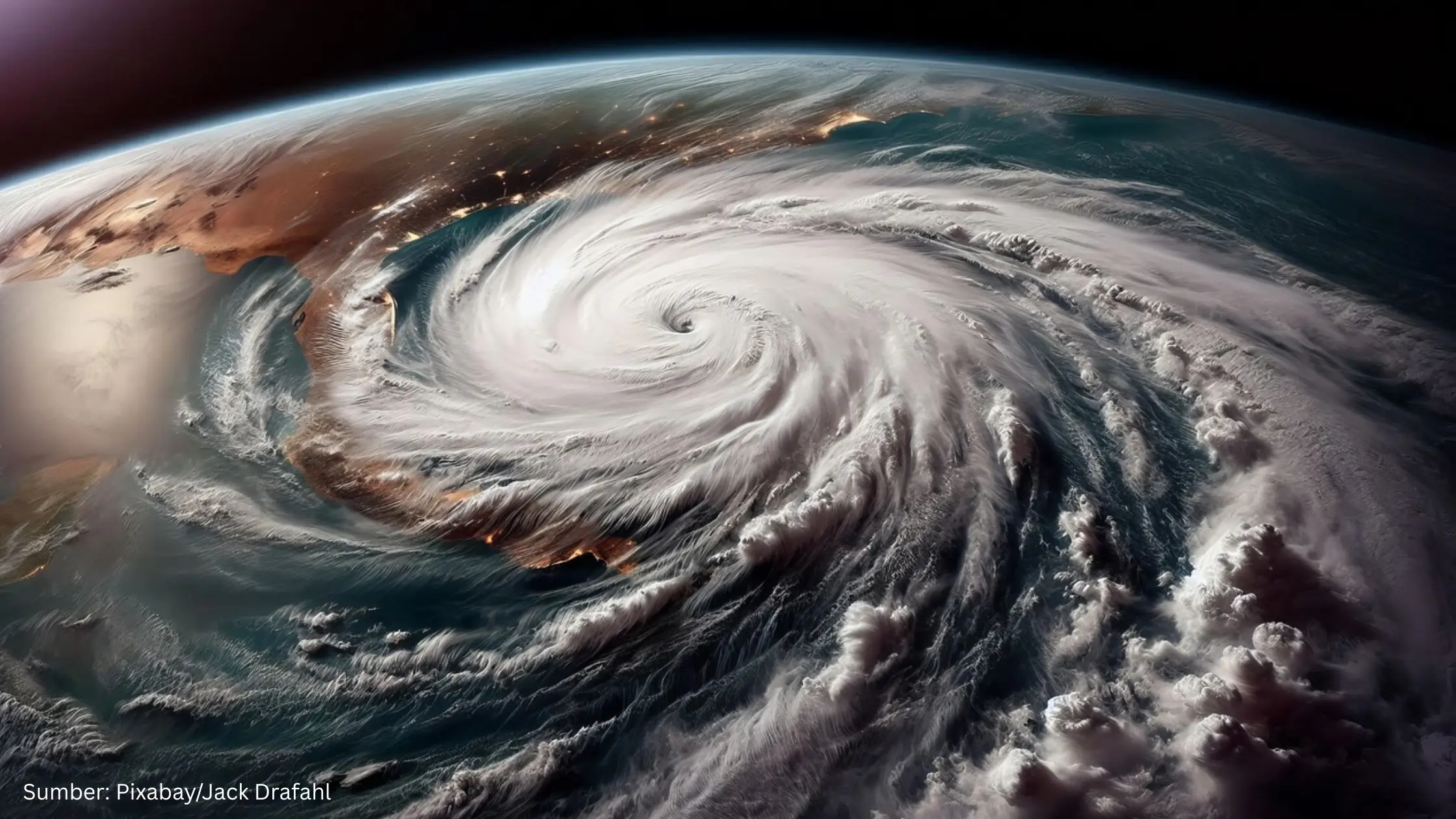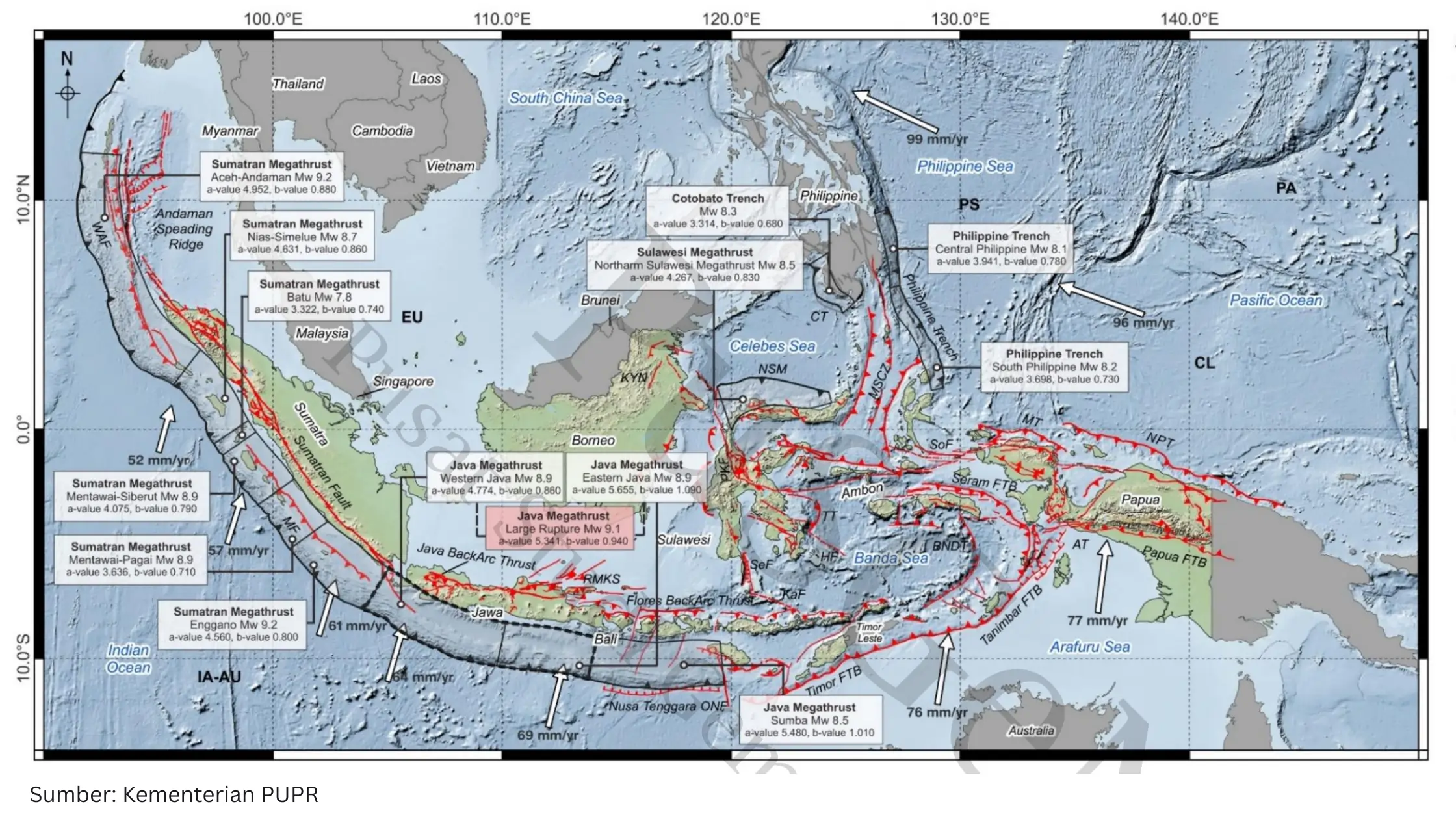Fenomena sound horeg yang kini menjalar dari darat ke lautan menjadi polemik serius, khususnya, setelah digelarnya festival tersebut di wilayah perairan Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain dianggap tidak memiliki izin dari otoritas kepolisian setempat, kegiatan yang mulanya merupakan bentuk hiburan masyarakat dalam perayaan Hari Raya Ketupat, bulan April 2025 yang lalu, kini menjadi sorotan karena dianggap mengganggu stabilitas ekologi laut, khususnya terhadap mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus.
Dengan suara yang bisa mencapai 135 desibel (dB), festival ini bukan hanya menimbulkan gangguan pendengaran bagi manusia di jarak dekat, tetapi juga menyebarkan gelombang tekanan akustik berbahaya di bawah permukaan laut. Saat gelombang suara asing dengan intensitas tinggi memasuki habitat mereka, kemampuan orientasi tersebut menjadi terganggu. Studi dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan bahwa kebisingan bawah laut yang ekstrem bisa menyebabkan disorientasi, terdampar, bahkan kematian pada paus dan lumba-lumba.
Sound Horeg Ancaman bagi Ekosistem Laut
Menurut International Fund for Animal Welfare (IFAW), gangguan suara seperti sound horeg sendiri dikategorikan sebagai polusi suara di laut yang dapat mengancam ekosistem yang ada. Padahal, studi yang dipublikasikan oleh WWF menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah laut Indonesia merupakan habitat penting atau jalur migrasi bagi sekitar 18 spesies paus serta 12 spesies lumba-lumba dan ambu. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu jalur migrasi dan perilaku alami mereka yang memanfaatkan ekolokasi untuk mobilisasi.
Kehadiran suara yang keras dan konstan dari sound horeg membuat sistem ekolokasi lumba-lumba dan paus rusak. Binatang-binatang ini menjadi mengalami disorientasi, kehilangan arah, gagal menemukan makanan, bahkan bisa tersesat jauh dari habitat atau rute migrasinya. Dalam konteks geospasial, ini berarti suara yang ditimbulkan dapat menjadi gangguan pada mobilitas dari peta mental para penghuni bawah laut tersebut.
Polusi suara laut bukan hanya merusak interaksi sosial dan orientasi, melainkan juga berpotensi menyebabkan cedera langsung pada hewan laut. Meskipun sound horeg tidak sekeras sonar militer atau seismic airguns yang digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas, tren ini bisa menjadi awal dari normalisasi polusi suara intensif di laut Indonesia.
International Fund for Animal Welfare menyebutkan bahwa paus dan lumba-lumba, jika terpapar suara keras mendadak, dapat panik dan berenang ke permukaan secara cepat. Hal ini menyebabkan mereka mengalami decompression sickness (penyakit dekompresi), yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas dalam jaringan tubuh. Dalam kasus ekstrem, ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, tuli permanen, hingga kematian dan terdampar di daratan.
Saat para mamalia ini mulai terdampar, kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi suara tidak berhenti pada individu hewan laut saja, tetapi menjalar hingga ke struktur rantai makanan yang ada di dasar laut. Misalnya, jika seekor paus mati di darat akibat disorientasi karena kebisingan maka tubuhnya tidak akan kembali ke dasar laut untuk menjadi sumber nutrisi bagi organisme, seperti terumbu karang, ikan, krustasea, dan mikroorganisme laut lainnya. Di sinilah pentingnya memahami laut sebagai sistem ekologi yang saling terhubung secara spasial dan temporal, bukan semata-mata lokasi untuk menggelar hiburan tanpa gangguan.
Perlu Adanya Regulasi yang Tegas
Ironisnya, di tengah semakin jelasnya bukti ilmiah mengenai dampak destruktif polusi suara terhadap ekosistem laut, baik Indonesia maupun dunia internasional masih menunjukkan ketertinggalan dalam merespons secara regulatif. Belum ada payung hukum yang benar-benar mampu menjawab kompleksitas persoalan ini, baik dari segi perlindungan ekologis maupun pengawasan aktivitas manusia di laut.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik dan tegas yang mengatur mengenai polusi suara di laut. Padahal, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai lebih dari 95.000 km, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kualitas lingkungan lautnya, bukan hanya dari polusi kimia dan plastik, melainkan juga dari ancaman akustik yang tersembunyi namun merusak.
Khusus untuk sound horeg di lautan, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, pada Juli 2024, sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval dan hiburan masyarakat. Namun, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek administratif, perizinan, dan ketertiban umum, bukan perlindungan lingkungan laut atau kesejahteraan satwa akuatik. Tak ada satu pun klausul dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan atau mempertimbangkan dampak ekosistem dari kebisingan yang ditimbulkan.
Ketiadaan regulasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa isu polusi suara laut belum masuk dalam radar kebijakan lingkungan nasional. Padahal, sebagai negara penanda tangan berbagai konvensi lingkungan internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjadikan perlindungan laut sebagai prioritas kebijakan.
Sementara untuk tatanan luar negeri, saat ini lembaga internasional mulai memberikan perhatian. Namun, sejauh ini belum ada instrumen yang benar-benar mengikat. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang merupakan perjanjian kelautan paling komprehensif dengan 168 negara anggota, mencantumkan perlindungan laut dalam Pasal 211. Namun, pasal ini masih bersifat normatif dan tidak secara eksplisit membahas polusi suara, apalagi menetapkan langkah-langkah konkret yang wajib diambil oleh negara-negara pihak.
Di sisi lain, International Maritime Organization (IMO), lembaga khusus PBB yang mengatur transportasi maritim, telah menyusun pedoman pengurangan kebisingan bawah laut dari kapal-kapal niaga. Pedoman ini mencakup strategi pengurangan kebisingan melalui desain kapal, konstruksi, modifikasi, dan pengoperasian, termasuk pengurangan kecepatan kapal. Namun, pedoman awal ini sayangnya tidak diadopsi secara luas oleh pelaku industri.
Sebagai respons, IMO kemudian merevisi pedoman tersebut dan meluncurkan experience-building phase (EBP) sejak 2023, dengan tujuan mengumpulkan data tentang praktik terbaik dan efektivitas penerapannya di lapangan. Meski merupakan langkah maju, sifatnya yang masih berupa fase “pengumpulan data” mencerminkan ketidakpastian dan ketidaktegasan dalam penegakan prinsip perlindungan terhadap gangguan kebisingan laut.
Laut Bukan Panggung Hiburan
Fenomena sound horeg di laut, sebagaimana terjadi di perairan Lekok, Pasuruan, bukan hanya cermin dari kebebasan berekspresi yang kebablasan, tetapi juga bentuk nyata dari abainya kita terhadap ekologi laut. Dengan intensitas suara mencapai 135 dB, festival ini bukan lagi sekadar pesta, melainkan sudah berubah menjadi ancaman spasial dan biologis bagi mamalia laut, seperti lumba-lumba dan paus. Dampaknya tidak berhenti pada gangguan komunikasi dan disorientasi, tetapi berlanjut pada kerusakan fisiologis hingga kematian dan terganggunya rantai makanan laut.
Sayangnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, respons terhadap polusi suara laut masih sangat minim dan tidak mengikat. Indonesia sebagai negara maritim belum memiliki satu pun regulasi komprehensif yang membahas secara eksplisit dampak kebisingan di bawah laut terhadap ekosistem. Sementara itu, pedoman internasional yang ada masih bersifat sukarela dan lemah dalam implementasi.
Dalam konteks ini, negara harus segera hadir. Indonesia membutuhkan regulasi yang kuat, progresif, dan berbasis sains untuk mencegah normalisasi polusi akustik di laut, termasuk larangan atau pembatasan terhadap kegiatan seperti sound horeg yang digelar di perairan terbuka. Regulasi semacam ini tidak hanya mendesak secara ekologis, tetapi juga esensial untuk membuktikan bahwa pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Laut bukanlah ruang kosong yang bebas digunakan tanpa batas. Ia adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup yang punya hak untuk hidup dalam sunyi yang lestari. Sudah saatnya kita berhenti membuat laut tuli oleh dentuman yang kita ciptakan sendiri.
sumber: Kompas TV, IFAW, WWF, Kab Pasuruan