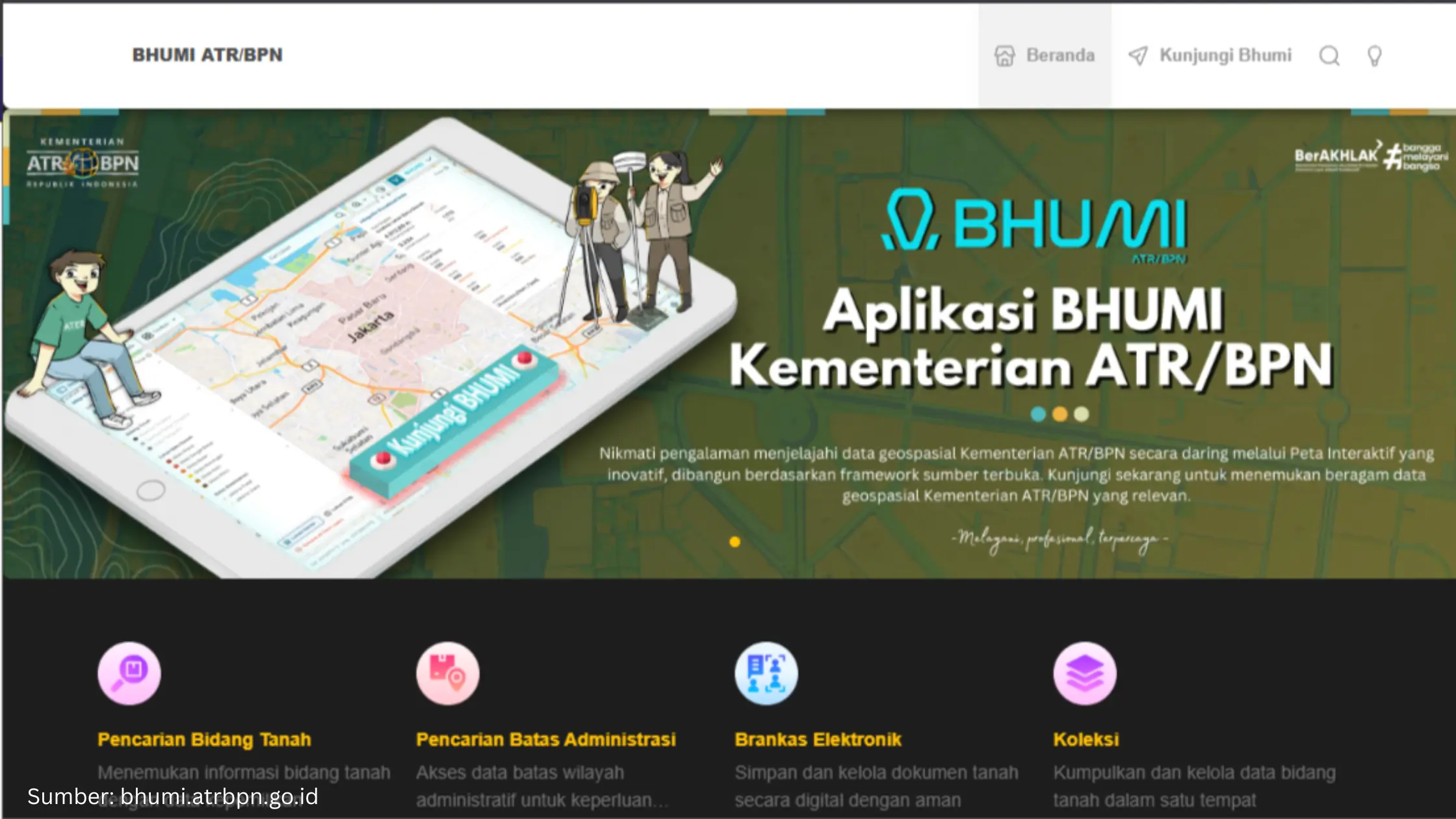Mengapa Sistem Peringatan Dini Bencana Kerap Gagal di Indonesia?
Hujan deras kembali mengguyur Jakarta pada Senin malam, 7 Juli 2025. BPBD DKI Jakarta mencatat jumlah genangan meningkat dari enam menjadi dua belas RT hanya dalam satu jam. Status Siaga 3 di Bendung Katulampa pun diumumkan, yang menandakan potensi banjir kiriman. Seperti biasa, aparat dikerahkan untuk memantau dan menyedot air. Namun, pola ini terus berulang tanpa ada pembaruan sistemik dalam mitigasi yang berbasis data dan spasial.
Kasus Jakarta hanyalah salah satu dari banyak contoh kegagalan sistem peringatan dini bencana (disaster early warning system/DEWS) di Indonesia. Dari tsunami di Palu 2018 yang sirenenya tak aktif, banjir bandang di Luwu 2024 yang tak terdeteksi dini meski wilayahnya dikenal rawan, hingga erupsi Gunung Semeru 2021 yang tidak disertai panduan evakuasi spasial, semuanya mencerminkan lemahnya integrasi geospasial dalam pengelolaan bencana. Padahal, data dan peta risiko umumnya sudah tersedia, tetapi tidak digunakan secara real-time maupun terhubung secara operasional lintas lembaga.
Negara dengan kerentanan bencana setinggi Indonesia seharusnya menjadikan DEWS sebagai garis pertahanan pertama. Namun kenyataannya, sistem ini masih sering gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Alarm tidak berbunyi, informasi datang terlambat, dan masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penyebabnya adalah keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, atau kurangnya pemanfaatan data spasial secara optimal?
- Ketimpangan Infrastruktur dan Fragmentasi Data
Salah satu akar persoalan adalah ketimpangan infrastruktur dan fragmentasi data. Banyak daerah rawan bencana justru kekurangan sensor bencana, seperti seismograf, radar cuaca, atau tide gauge. Bahkan, beberapa perangkat penting dibiarkan rusak atau hilang begitu saja. Ketimpangan ini diperburuk oleh fakta bahwa masing-masing lembaga, baik pusat maupun daerah, mengelola data spasialnya sendiri-sendiri. Tidak ada satu sistem terpadu yang mampu menyatukan informasi penting, seperti peta risiko, titik evakuasi, dan posisi sensor secara lintas instansi. Akibatnya, informasi yang seharusnya menyelamatkan justru datang dalam potongan yang tak sinkron secara spasial maupun temporal.
- DEWS Masih Dilihat sebagai Sistem Deteksi Saja
Masalah lainnya terletak pada cara pandang terhadap DEWS yang terlalu sempit. Banyak pemerintah daerah masih melihatnya sekadar sebagai alat pendeteksi ancaman, bukan sebagai sistem pendukung keputusan berbasis spasial. Padahal, teknologi geospasial memungkinkan simulasi rute evakuasi tercepat, pemetaan jalur aman, dan penentuan titik kumpul secara presisi. Namun pendekatan, seperti network analysis atau spatial simulation, masih jarang digunakan dalam kebijakan mitigasi. Akibatnya, saat bencana benar-benar datang, keputusan yang diambil cenderung reaktif dan bersifat improvisasi, bukan berbasis data.
- Tantangan Geografi dan Shadow Zone
Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat kompleks. Ribuan pulau, pegunungan, lembah, hingga wilayah terpencil menciptakan banyak zona yang tidak terjangkau sinyal peringatan atau jaringan komunikasi. Dalam konteks ini, shadow zone bukan sekadar istilah teknis, melainkan juga realitas sehari-hari bagi banyak warga di pedalaman. Sistem DEWS tidak bisa hanya disebarkan secara seragam tanpa memperhitungkan topografi dan aksesibilitas. Diperlukan perencanaan coverage mapping yang cermat agar sistem ini benar-benar inklusif secara spasial.
- Rendahnya Literasi Geospasial Masyarakat
Namun, sebaik apapun sistem teknologi yang dibangun, semuanya akan sia-sia tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Rendahnya literasi geospasial di tingkat akar rumput menjadi titik lemah sistem peringatan dini kita. Banyak warga tidak tahu cara membaca peta risiko, memahami simbol evakuasi, atau merespons sirene bencana. Kegagapan ini bukan semata karena kurangnya edukasi, melainkan karena pendekatan edukasi yang masih top-down. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan secara langsung melalui community mapping, pelatihan spasial, dan penyusunan rencana evakuasi bersama. Ketika masyarakat merasa memiliki peta yang mereka buat sendiri, kesiapsiagaan akan tumbuh dari bawah ke atas.
- Belum Terbangunnya Sistem Geospasial Cerdas
Di sisi lain, Indonesia juga belum sepenuhnya mengadopsi sistem geospasial cerdas yang sudah tersedia secara global. Teknologi seperti real-time GIS, pengindraan jauh, kecerdasan buatan, hingga IoT sejatinya sudah dapat digunakan untuk mendeteksi anomali spasial-temporal. Namun sayangnya, sistem kebencanaan nasional masih banyak bergantung pada prosedur manual dan data statis. Padahal, negara-negara lain sudah membuktikan efektivitas sistem berbasis AI dan cloud untuk mempercepat prediksi dan respon bencana. Tanpa keberanian untuk mengintegrasikan teknologi tersebut, Indonesia hanya akan terus tertinggal dalam menghadapi bencana yang makin dinamis.
Waktunya Beralih ke Model Mitigasi
Melihat berbagai hambatan mulai dari ketimpangan infrastruktur, lemahnya integrasi data spasial, tantangan geografis, hingga rendahnya literasi masyarakat, jelas bahwa kegagalan sistem peringatan dini di Indonesia bukan semata-mata karena kurangnya teknologi. Masalah utamanya justru terletak pada kegagalan dalam membangun ekosistem kebencanaan yang berbasis kolaborasi, keterbukaan data, dan kecerdasan spasial. Sistem yang seharusnya menyelamatkan justru tersendat karena tidak pernah benar-benar dipandang sebagai investasi strategis nasional.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia meninggalkan pendekatan reaktif dan beralih ke model mitigasi bencana yang proaktif dan berbasis geospasial. Tanpa integrasi teknologi, partisipasi warga, dan tata kelola data yang solid, peringatan dini hanya akan menjadi informasi yang terlambat sampai. Dalam konteks bencana, keterlambatan sering kali berarti kehilangan nyawa.
Sumber: Detik.com