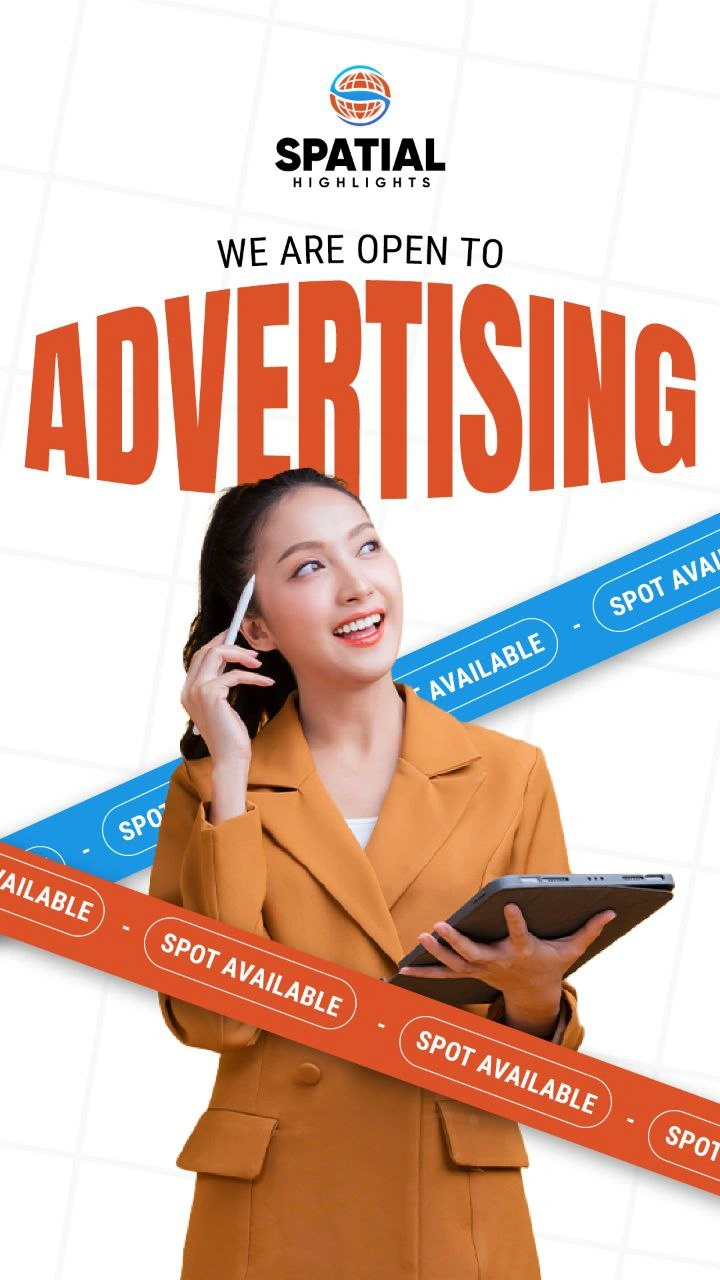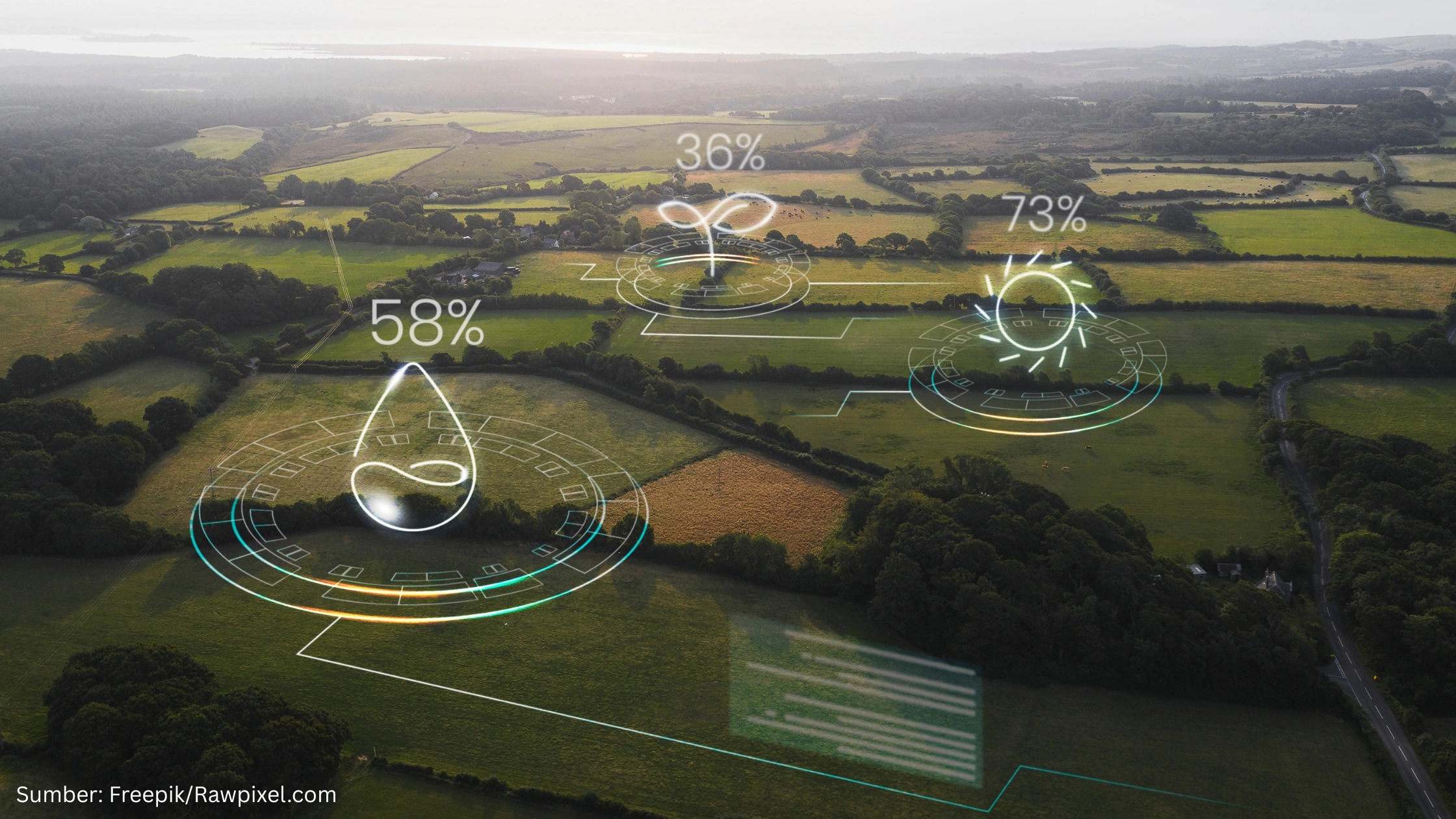Jurang Kesejahteraan Tercermin dari Garis Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia
Perbatasan sejatinya hanya sebuah garis di peta, namun realitas di lapangan menunjukkan jurang kesejahteraan yang nyata antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut terlihat jelas dari unggahan Instagram balikpapanfolks, yang memperlihatkan perbandingan di perbatasan Sambas, Paloh, Kalimantan Barat. Pada sisi Indonesia, jalan masih berupa tanah, sementara di sisi Malaysia jalannya sudah beraspal mulus lengkap dengan pagar pembatas. Kontras visual ini tidak sekadar menjadi tontonan, tetapi juga potret nyata tentang ketimpangan pembangunan yang begitu dekat, namun jarang mendapat sorotan luas.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang memberikan perhatian serius terhadap daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Masyarakat yang tinggal di perbatasan akhirnya merasakan langsung bagaimana jurang kesejahteraan itu tampak di depan mata mereka, seakan menjadi pembeda tegas antara kualitas pembangunan di dua negara bertetangga. Ironisnya, daerah yang seharusnya menjadi etalase kedaulatan justru terlihat tertinggal sehingga memperkuat kesan bahwa pembangunan Indonesia belum sepenuhnya merata hingga ke garis terluarnya.

Apakah Kendala Pemerintah di Perbatasan?
Dari perspektif geospasial, infrastruktur di wilayah perbatasan bukan hanya soal konektivitas, melainkan juga simbol kehadiran negara sekaligus penegasan kedaulatan. Menurut data dari Bina Marga, pembangunan jalan paralel sepanjang 811 kilometer di Kalimantan Barat sejak 2020 merupakan bagian dari upaya membuka keterisolasian serta memperkuat fungsi pertahanan dan ekonomi lokal. Namun, data Kementerian PUPR pada 2021 mencatat masih ada 277 kilometer jalan yang berupa tanah, 172 kilometer berupa agregat, dan hanya 363 kilometer yang beraspal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun ada progres, jurang infrastruktur di lapangan tetap nyata, bahkan di wilayah strategis yang seharusnya menjadi wajah depan Indonesia di mata negara tetangga.
Pemerintah memang telah mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun pada 2021 untuk pembangunan perbatasan, termasuk terminal barang internasional Nanga Badau senilai sekitar Rp100 miliar. Akan tetapi, anggaran tersebut belum cukup menjawab persoalan mendasar.
Banyak ruas jalan, terutama di Sambas–Paloh, masih belum mantap dan rawan rusak akibat kondisi alam yang ekstrem. Okezone.news melaporkan bahwa abrasi di sepanjang pantai Desa Matang Danau, Paloh, yang mengikis garis pantai hingga 5–8 meter per tahun, menambah beban kerusakan karena mengancam jalan utama sekaligus lahan pertanian warga. Kendala geografis, iklim, serta tata kelola pembangunan yang belum berbasis penuh pada analisis geospasial membuat infrastruktur di perbatasan rentan sehingga memperlambat proses pemerataan dan menjadikan perbatasan tetap tampak tertinggal.
Saatnya Geospasial Ambil Peran di Pembangunan Wilayah Perbatasan
Walaupun sejumlah program pembangunan sudah digulirkan, wilayah perbatasan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang membuatnya tertinggal. Kondisi ini menuntut adanya analisis geospasial yang lebih serius untuk merancang pembangunan secara tepat sasaran. Tanpa perencanaan berbasis data geospasial, infrastruktur yang dibangun sering kali tidak bertahan lama, misalnya jalan yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan kondisi tanah, curah hujan, maupun ancaman abrasi. Akibatnya, anggaran negara banyak terserap untuk perbaikan berulang, bukan untuk pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemanfaatan geospasial harus ditempatkan pada posisi yang lebih strategis dalam pembangunan perbatasan. BIG bersama Kementerian PUPR, BNPP, dan lembaga terkait sebenarnya sudah memiliki perangkat yang memadai, mulai dari peta dasar, citra satelit, hingga sistem informasi geografis (SIG). Dengan dukungan data tersebut, jalur infrastruktur bisa ditentukan secara lebih presisi, risiko bencana dapat diminimalkan, dan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan infrastruktur dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan, bukan sekadar responsif terhadap masalah yang sudah terjadi.
Dengan demikian, data dan analisis geospasial harus dijadikan pijakan utama dalam merancang infrastruktur yang kokoh, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di perbatasan. Pembangunan berbasis geospasial akan mengubah citra perbatasan dari daerah tertinggal menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus penguatan kedaulatan negara. Lebih dari sekadar jalan atau jembatan, proyek infrastruktur perbatasan bisa menjadi strategi geopolitik yang menghubungkan wilayah, memperkuat kehadiran negara, dan sekaligus memperkecil kesenjangan kesejahteraan dengan negara tetangga.