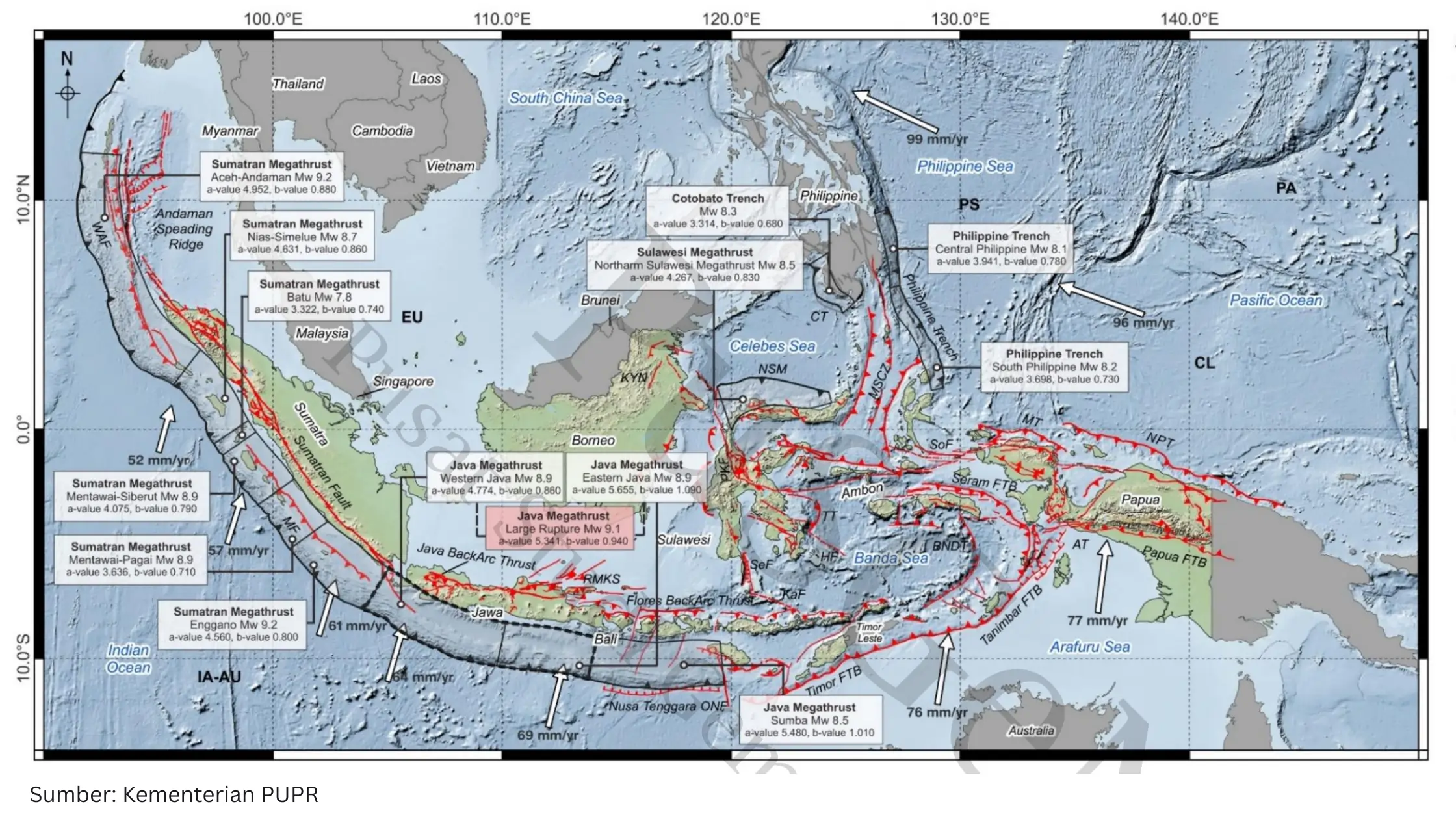Yogyakarta, yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar dengan biaya hidup yang relatif rendah dan atmosfer egaliter, kini tengah mengalami tekanan urbanisasi yang pesat. Pembangunan infrastruktur, derasnya aliran investasi, dan dorongan pariwisata menjadikan wajah kota ini berubah drastis dalam waktu singkat.
Salah satu dampak paling mencolok dari perubahan ini adalah kenaikan harga hunian yang melonjak tajam, terutama di kawasan strategis dan peri-urban seperti Kabupaten Sleman. Pertanyaannya, apakah gentrifikasi menjadi penyebab utama dari semua ini?
Gentrifikasi merupakan fenomena transformasi ruang kota yang kompleks dan multidimensional. Ia melibatkan proses masuknya investasi atau modal ke dalam kawasan yang semula dihuni oleh kelompok berpendapatan rendah, yang kemudian diikuti oleh pembangunan apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, hingga hunian eksklusif.
Secara fisik, gentrifikasi menciptakan wajah kota yang tampak modern dan tertata. Namun, dari sisi sosial, ia sering kali membawa luka: penggusuran, keterusiran, dan hilangnya ruang hidup bagi masyarakat lokal yang tidak mampu bersaing dalam kompetisi pasar properti yang kian eksklusif.
Jejak Gentrifikasi di Kabupaten Sleman
Pendekatan geospasial dapat memperlihatkan bagaimana pola gentrifikasi menjalar dari pusat kota Yogyakarta menuju kawasan peri-urban seperti Sleman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah hotel berbintang di Sleman meningkat dari 26 unit pada 2015 menjadi 65 unit pada 2020. Untuk hotel non-bintang, jumlahnya melonjak dari 363 menjadi 715 unit pada periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan tekanan pembangunan yang luar biasa besar di wilayah yang sebelumnya lebih didominasi oleh hunian masyarakat lokal.
Hal ini menunjukan alih fungsi lahan yang signifikan dari kawasan permukiman menjadi zona komersial dan jasa. Kawasan seperti Karangwuni di Kecamatan Depok, Sleman, yang dulunya merupakan kampung dengan identitas sosial kental, kini menjadi lokasi apartemen eksklusif, kos-kosan mahasiswa elite, dan properti spekulatif. Fenomena ini memicu ketimpangan akses terhadap lahan, krisis air, dan bahkan konflik horizontal antarwarga.
Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Auliani Fauziatunnisa dan tim dari Universitas Gadjah Mada mengungkap wajah lain dari pembangunan di Sleman. Melalui wawancara dengan warga Karangwuni, mereka menemukan dua bentuk keterusiran yang dialami masyarakat, keterusiran fisik akibat penggusuran dan keterusiran sosial akibat perubahan struktur budaya dan ikatan komunitas.
Ketua RT, warga sepuh, hingga tokoh penolak pembangunan apartemen seperti Pak Wisnu dari PKWTU (Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara) menyuarakan kekhawatiran yang sama. Dirinya mengungkapkan, Karangwuni bukan lagi kampung, melainkan menjadi zona ekonomi baru yang tidak berpihak pada warga asli. Kegiatan budaya hilang, rasa kebersamaan luntur, dan banyak warga menjual rumahnya karena tekanan harga dan tawaran dari investor.
Selain itu, gentrifikasi tidak hanya soal visual kota dan perubahan fisik saja. Fenomena ini juga berdampak pada ketimpangan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki Gini Ratio tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, yakni 0,434. Ini artinya, meski kota ini tampak maju dan modern, kesenjangan antara kaya dan miskin kian melebar.
Permintaan terhadap hunian sementara oleh mahasiswa, wisatawan, dan pekerja luar daerah menciptakan pasar properti yang tidak lagi terjangkau oleh warga lokal. Rumah-rumah yang dulunya tempat tinggal kini berubah fungsi menjadi kos eksklusif atau homestay, menyebabkan pergeseran sosial secara struktural.
Kurangnya Perspektif Sosial dalam Tata Ruang
Gentrifikasi di Yogyakarta mencerminkan kurangnya sensitivitas dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan. Pemerintah cenderung melihat investasi sebagai satu-satunya indikator kemajuan, sementara suara masyarakat terdampak sering kali diabaikan. Bahkan, dalam banyak kasus, konflik sosial dianggap sebagai masalah sampingan yang bisa diselesaikan belakangan.
Melihat pola ekspansi kota dan gentrifikasi di Yogyakarta, terutama di kawasan Sleman, dibutuhkan perencanaan kota yang tidak hanya fokus pada nilai ekonomi ruang, tetapi juga pada nilai sosial, budaya, dan ekologi. Gentrifikasi tidak bisa sepenuhnya dihentikan, tetapi dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui kebijakan yang inklusif.
Pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk merumuskan tata ruang yang adil, yang memberi ruang hidup bagi semua kelas sosial, menghormati hak warga lokal, dan tetap menjaga identitas budaya kota.
Sumber: Philosofisonline, Caritra, UGM, Researchgate