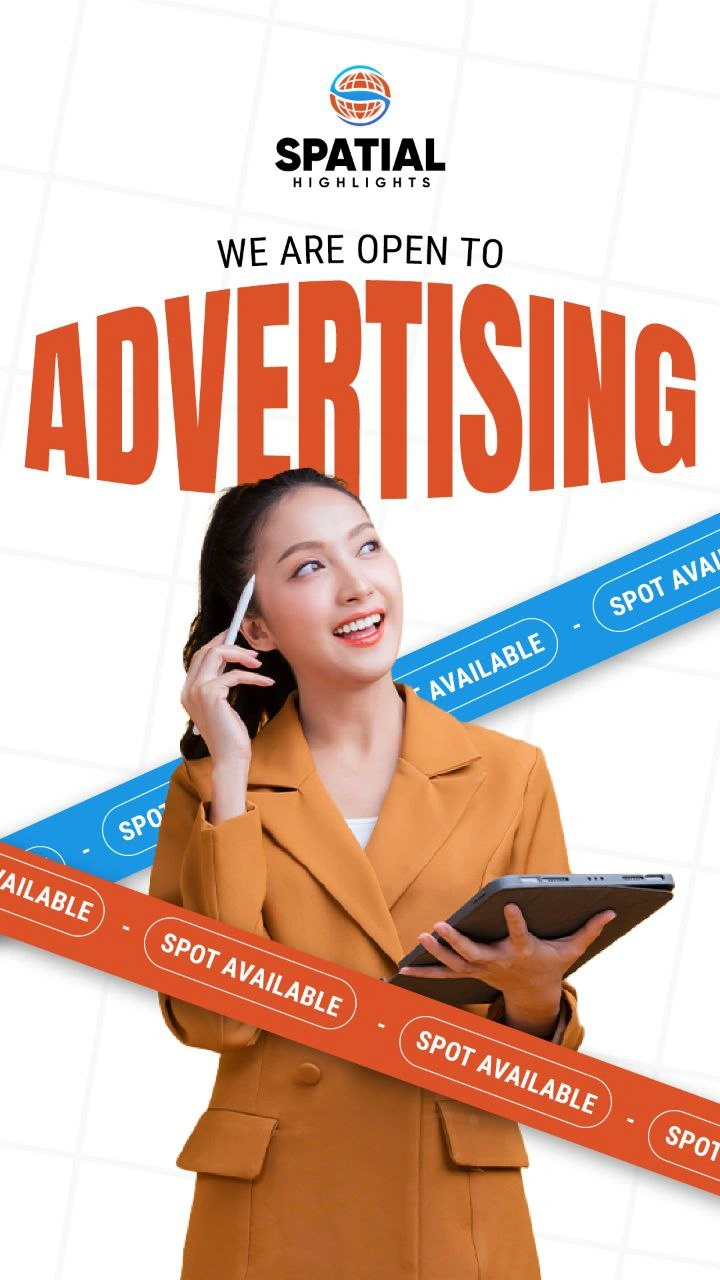Analisis Spasial Kereta Cepat Whoosh, antara Konektivitas Ruang dan Rasionalitas
Proyek Kereta Cepat Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung menjadi salah satu simbol ambisi modernisasi transportasi Indonesia. Jalur sepanjang 142 kilometer ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antarkota menjadi kurang dari satu jam, sekaligus menjadi tonggak kemajuan teknologi perkeretaapian nasional.
Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat dinamika spasial yang kompleks. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi geografis, tata letak stasiun, hingga dampak ruang dan sosial ekonomi yang muncul di sepanjang koridor jalur.
Secara geografis, jalur kereta cepat Whoosh membentang dari Jakarta hingga Tegalluar, Kabupaten Bandung, melewati wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian besar lintasan melintasi daerah perbukitan dan lembah yang memiliki tingkat kerentanan geoteknik tinggi, terutama di kawasan Purwakarta hingga Padalarang. Berdasarkan laporan Askara, untuk mengatasi kondisi tersebut, lebih dari 60 persen trase dibangun di atas viaduk dan terowongan panjang.
Kondisi tanah yang labil, curah hujan tinggi, serta risiko gempa di Jawa Barat menjadikan proyek ini berbiaya sangat besar dan teknis pelaksanaannya rumit. Beberapa kali dilakukan revisi desain serta tambahan biaya yang mencapai miliaran dolar. Dari sisi spasial, hal ini menunjukkan bahwa jalur kereta cepat dibangun di atas bentang alam yang tidak ideal bagi pembangunan berkecepatan tinggi.
Lokasi dan Aksesibilitas
Dari perspektif tata ruang, keberadaan stasiun menjadi elemen kunci dalam menentukan efisiensi sistem transportasi. Jalur Whoosh memiliki empat stasiun utama: Halim di Jakarta Timur, Karawang di Kabupaten Karawang, Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, dan Tegalluar di Kabupaten Bandung. Namun, lokasi keempat stasiun tersebut menimbulkan persoalan aksesibilitas.
Stasiun Halim, contohnya, tidak berada di pusat Jakarta sehingga penumpang dari wilayah lain tetap harus menempuh perjalanan tambahan untuk mencapai lokasi keberangkatan. Hal serupa terjadi di Bandung, di mana Stasiun Tegalluar terletak di pinggiran kota dan belum terhubung optimal dengan sistem transportasi publik yang memadai. Akibatnya, waktu tempuh total dari pusat kota ke stasiun bisa hampir menyamai durasi perjalanan kereta cepat itu sendiri.
Kondisi ini menimbulkan “paradoks spasial”. Meskipun Whoosh dirancang untuk kecepatan tinggi, konektivitas last mile yang kurang efisien mengurangi daya tariknya bagi pengguna. Akses yang terbatas juga berimplikasi terhadap rendahnya volume penumpang harian, yang dilaporkan Independen Media hanya berkisar antara 16.000 hingga 18.000 orang, jauh di bawah proyeksi awal sekitar 40.000 penumpang per hari.
Dimensi Ekonomi Ruang dan Beban Finansial
Masalah spasial tidak hanya berkaitan dengan lokasi fisik, tetapi juga dengan dimensi ekonomi ruang. Proses pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi lonjakan biaya proyek. Sebagian besar lahan yang dilalui Whoosh merupakan tanah milik masyarakat atau swasta dengan nilai sosial dan ekonomi tinggi sehingga proses negosiasi berlangsung panjang dan memakan biaya besar. Di Indonesia, biaya pembebasan lahan bisa mencapai 10–15 persen dari total anggaran, jauh lebih tinggi dibanding di Tiongkok yang hanya sekitar dua persen.
Biaya yang membengkak, diikuti oleh realisasi penumpang yang tidak sesuai harapan, menimbulkan beban finansial bagi operator dan membuka kemungkinan intervensi keuangan negara, meski proyek ini semula diklaim tanpa menggunakan dana APBN. Dari sudut pandang tata ruang, hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara investasi besar dalam infrastruktur dan manfaat spasial yang dihasilkan.
Peluang Transit-Oriented Development
Meski diwarnai sejumlah kendala, proyek Whoosh tetap membawa potensi besar terhadap transformasi ruang dan ekonomi wilayah. Peningkatan konektivitas antara Jakarta dan Bandung dapat membuka peluang pengembangan kawasan baru di sepanjang koridor, khususnya di sekitar stasiun-stasiun utama. Dengan pendekatan transit-oriented development (TOD), kawasan seperti Tegalluar atau Padalarang berpotensi menjadi simpul pertumbuhan baru, memadukan fungsi hunian, komersial, dan rekreasi.
Namun, agar potensi tersebut terwujud, integrasi spasial menjadi kunci. Pengembangan kawasan stasiun perlu disertai jaringan transportasi pengumpan yang efisien, tata guna lahan yang adaptif, serta perencanaan kota yang berorientasi pada konektivitas. Tanpa itu, proyek besar ini berisiko menjadi sekadar jalur transportasi cepat tanpa manfaat ruang yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya.