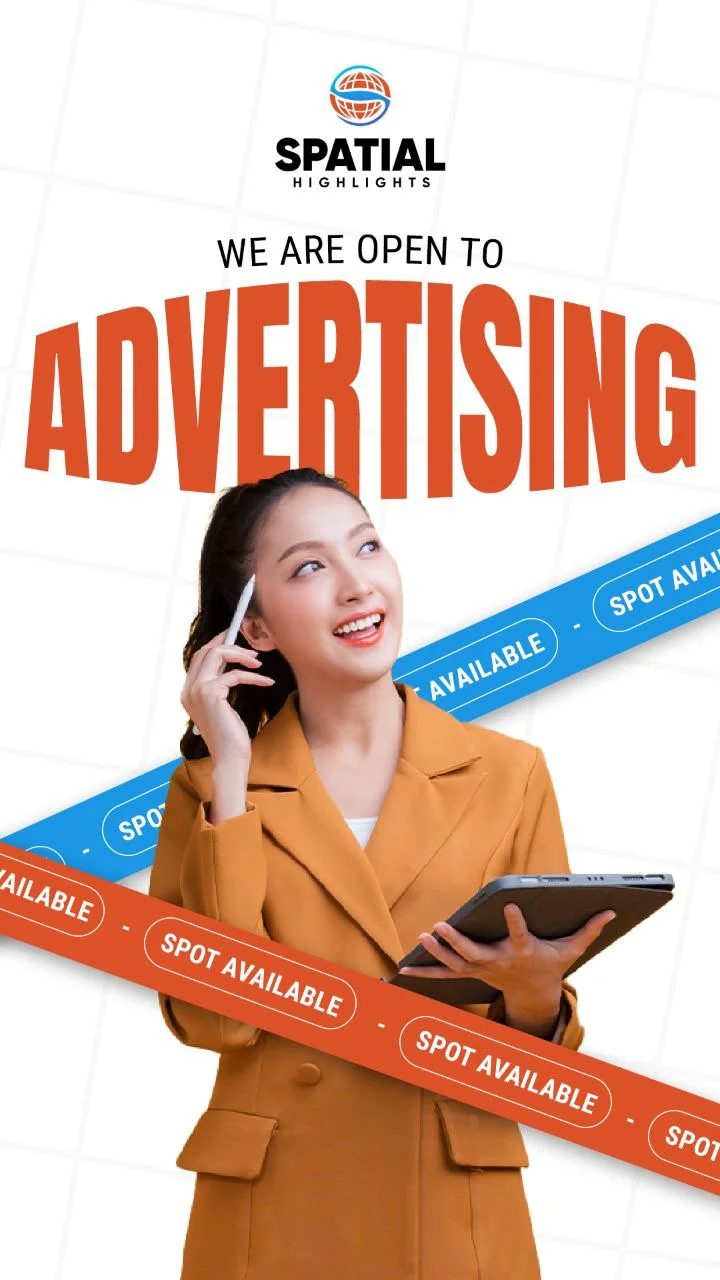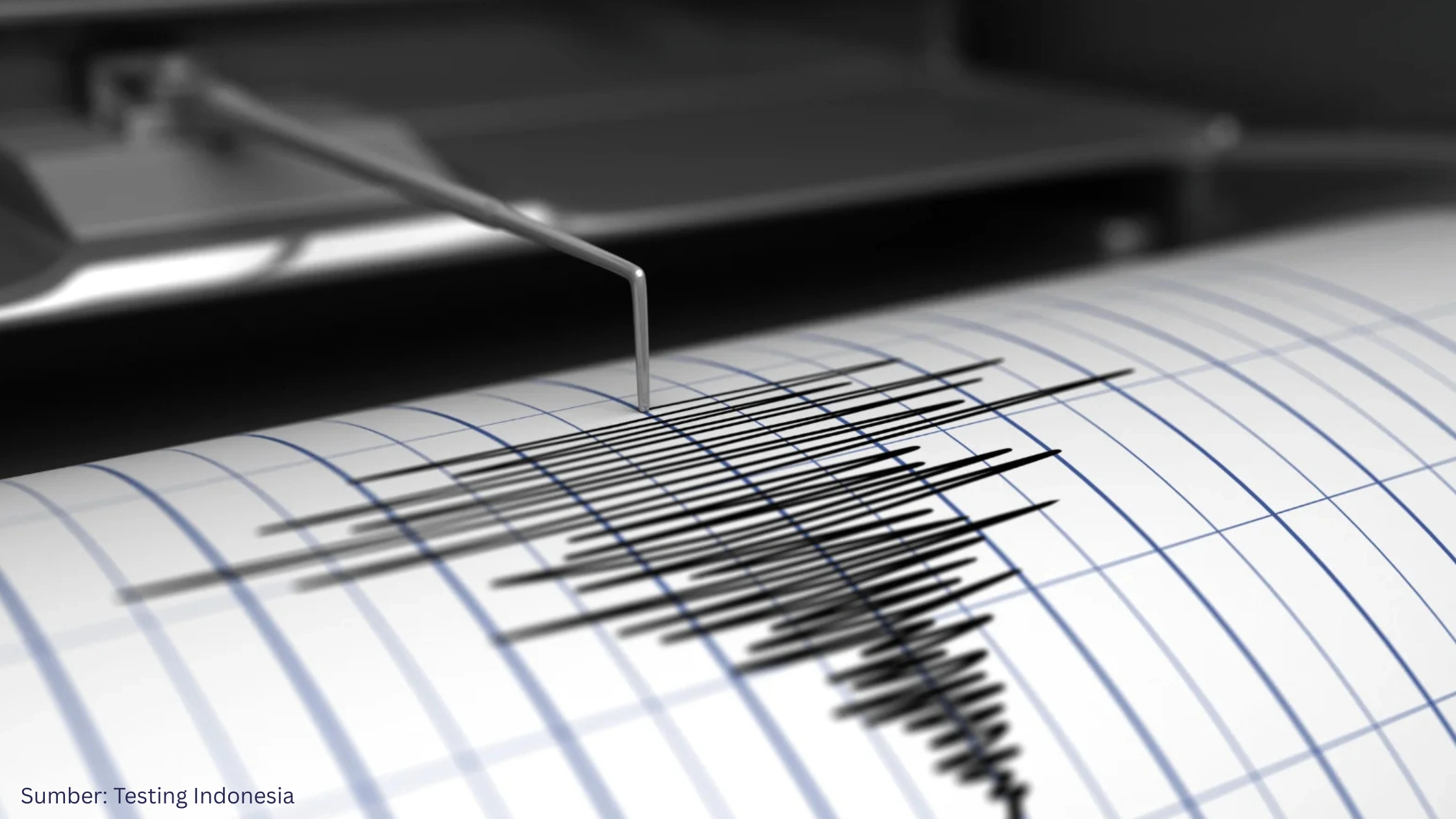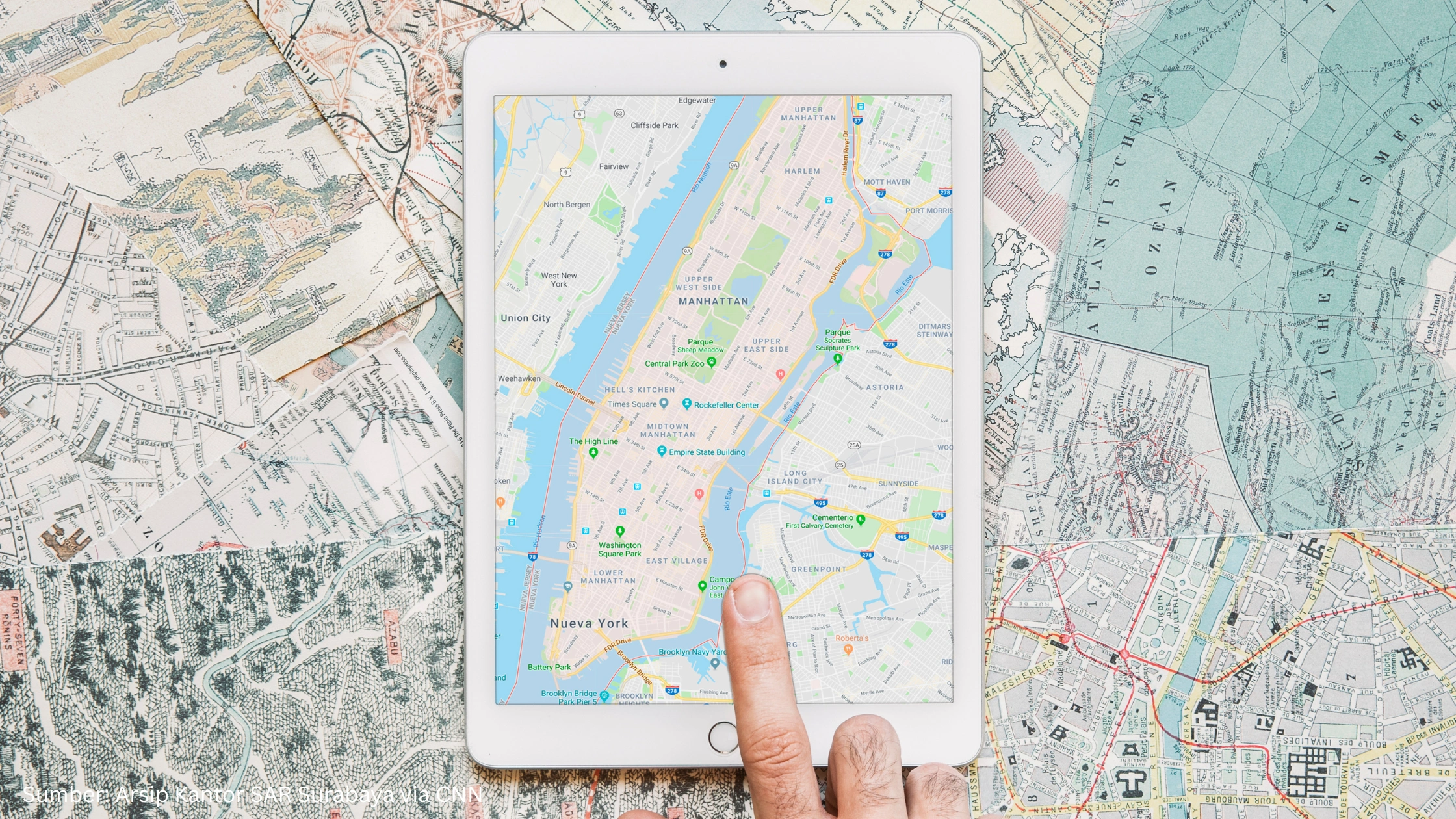Respons Fenomena Gempa Rusia, Dosen Geodesi UGM: Indonesia Masih Perlu Banyak Belajar
Gempa berkekuatan magnitudo 8,8 yang mengguncang wilayah Rusia baru-baru ini memicu gelombang tsunami lintas samudra dan menggetarkan kewaspadaan global. Negara-negara di lingkar Pasifik bergerak cepat. Jepang mengevakuasi ribuan warga di sekitar PLTN Fukushima, Amerika Serikat langsung menerapkan status siaga nasional, dan Hawaii menutup pelabuhan setelah dihantam gelombang setinggi 1,74 meter.
Peristiwa ini menegaskan bahwa bencana alam kini tak lagi mengenal batas geografis. Negara-negara yang terpapar risiko serupa menunjukkan betapa pentingnya sistem mitigasi yang tangguh, mulai dari teknologi peringatan dini hingga koordinasi lintas sektor dan literasi publik yang tinggi.
Indonesia sendiri berada di kawasan yang lebih rawan dibanding Rusia. Negara ini dilintasi oleh pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, menjadikannya salah satu wilayah dengan risiko gempa dan tsunami tertinggi di dunia. Namun, kesiapan menghadapi bencana masih jauh dari ideal.
Baca juga: Gempa Dahsyat Rusia Sebabkan Ancaman Tsunami Global
“Indonesia masih harus banyak berbenah, terutama dari sisi sumber daya manusia dan teknologi mitigasi,” ujar Cecep Pratama, Dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Cecep lebih lanjut mengatakan bahwa Indonesia memang telah memiliki sekitar 400 sensor GNSS dan ratusan stasiun pasut di sepanjang pesisir. Namun, sistem tersebut dinilai belum memadai untuk mendeteksi tsunami secara cepat, terutama pada skenario gempa megathrust di selatan Jawa yang bisa memicu tsunami dalam waktu 30–40 menit.
“Yang masih absen dari sistem deteksi Indonesia adalah teknologi seafloor GNSS atau acoustic GNSS. Alat ini, yang telah digunakan Jepang sejak 2011, mampu mendeteksi pergeseran dasar laut dalam hitungan detik dan memberikan data akurat untuk prediksi tsunami. Ketiadaan alat ini di Indonesia disebabkan oleh tingginya biaya dan minimnya prioritas pada riset infrastruktur mitigasi bawah laut,” ujar Cecep ketika ditemui Spatial Highlights di Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Dosen yang berfokus pada ilmu kebencanaan tersebut mengatakan aspek sosial budaya masyarakat juga penting sebagai salah satu unsur dalam upaya mitigasi bencana. “Komunitas-komunitas lokal di Indonesia sebenarnya telah memiliki kearifan dalam menghadapi bencana sejak ratusan tahun lalu. Namun, pengetahuan itu sering kali terputus dari sistem mitigasi modern,” lanjut Cecep.
Lulusan studi doktoral Nagoya University itu juga mengatakan mitigasi bencana erat kaitannya dengan pemanfaatan data geospasial dalam tata ruang. Peta sumber dan bahaya gempa nasional terbaru yang diluncurkan Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen) pada 2024 menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Contohnya terlihat di Lembang, Bandung, di mana zona bahaya sesar Lembang memiliki buffer zone sejauh 250 meter yang tidak boleh dibangun. Di Palu, zona sesar bahkan lebih sempit, hanya 12 meter, karena jalurnya sudah dipetakan dengan jelas. Namun, ketidaktahuan terhadap informasi sesar bisa berakibat fatal, seperti dalam kasus gedung PLN yang hancur akibat berdiri tepat di atas sesar aktif saat gempa Palu 2018,” tambah Cecep.
Di sisi regulasi, Cecep mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki SNI 1726:2019 yang mengatur ketahanan gempa untuk struktur bangunan. Namun, pembaruan regulasi ini harus mengikuti perkembangan terbaru dari peta bahaya dan hasil riset. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jembatan wajib dirancang berdasarkan potensi percepatan gempa yang spesifik.
“Misalnya, jika suatu daerah memiliki potensi goncangan hingga 1,5 G, maka struktur bangunan harus mampu menahan beban lebih dari itu. Namun, implementasi di lapangan belum merata dan masih banyak bangunan yang didirikan tanpa memperhatikan regulasi," terang Cecep.