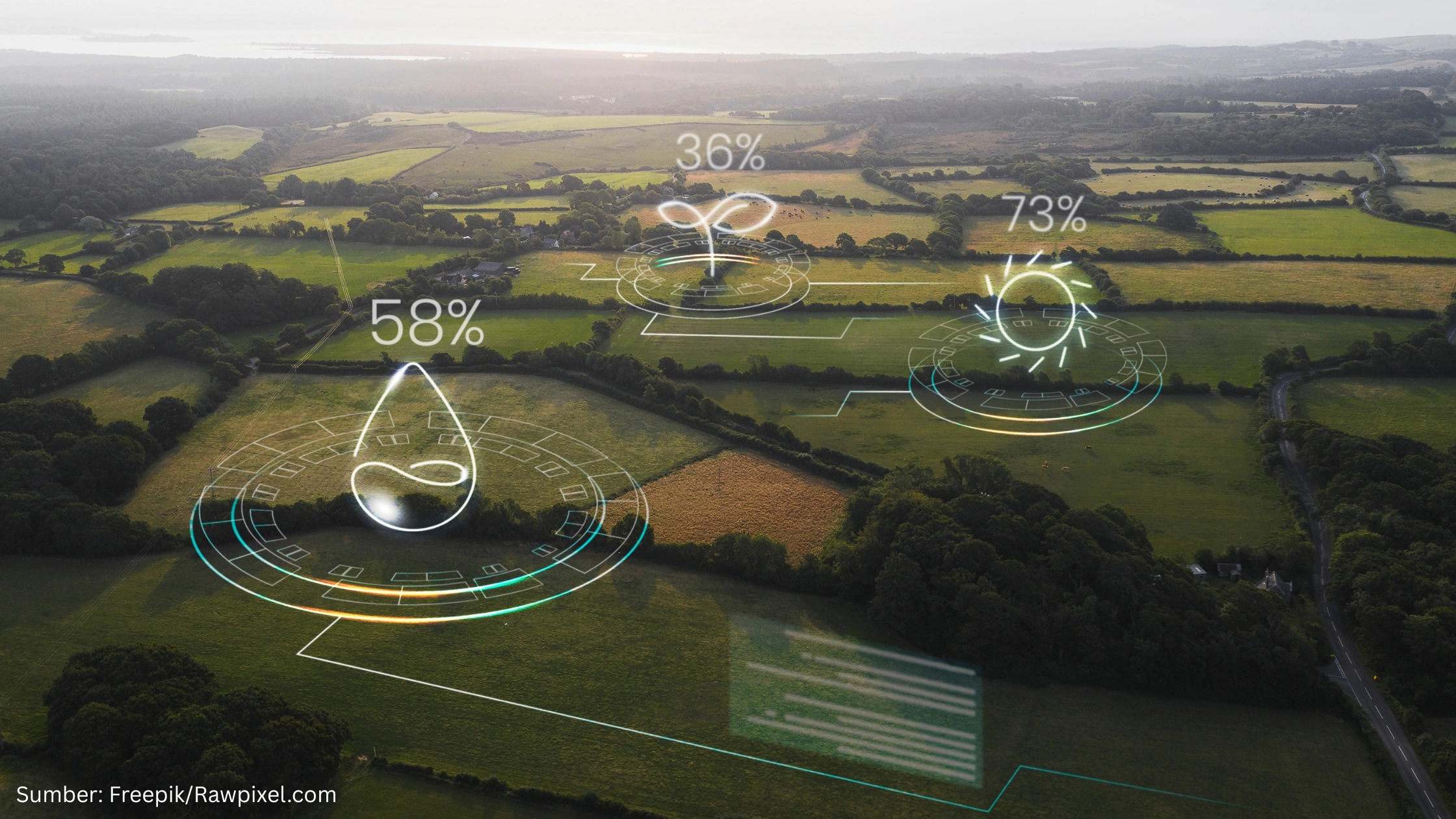Mengapa Pulau-Pulau Kecil Seharusnya Tidak Dieksploitasi?
Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mencabut izin dari empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, sebuah kawasan konservasi laut yang juga ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Hal ini dilakukan setelah Greenpeace dan masyarakat mengungkap adanya pelanggaran lingkungan, seperti deforestasi dan sedimentasi berbahaya.
Meskipun di Pulau Gag masih diperbolehkan untuk aktivitas tambang karena dianggap berada di luar zona geopark, aktivitas eksploitasi di pulau-pulau kecil, seperti Kawe dan Manuran, telah menyebabkan kerusakan serius, seperti keruhnya perairan, erosi pantai, hingga garis pantai yang berubah bentuk. Hal ini bukan sekadar persoalan praktik tambang, suara masyarakat, atau jarak ke destinasi wisata, sebab problemnya ada pada karakter pulau kecil itu sendiri yang seharusnya tidak dieksploitasi.
Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau-pulau dengan luas hingga 2.000 km² digolongkan sebagai “pulau kecil” dan memiliki perlindungan hukum ketat. Pasal 35 huruf i–k melarang eksploitasi baik berupa penambangan pasir, minyak, gas, maupun mineral di wilayah ini.
Mahkamah Konstitusi telah memperkuat hukum ini, menyatakan bahwa norma tersebut konstitusional karena pulau-pulau kecil punya karakter rentan dan risiko bencana yang tinggi. Otoritas lokal wajib mempertimbangkan hal ini saat mengeluarkan izin.
Berikut daftar pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km² yang telah terancam atau terkena tambang serta sejenisnya.
- Papua
Pulau Gag dengan luas 65 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
Pulau Manuran dengan luas 7,46 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
Pulau Kawe dengan luas 47 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
Pulau Batang Pele dengan luas 20 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
- Sumatra
Pulau Subi Besar dengan luas 110 km² digunakan sebagai lokasi tambang pasir kuarsa.
Pulau Karimun Besar dengan luas 126 km² digunakan sebagai lokasi tambang timah.
- Maluku
Pulau Mabuli dengan luas 2,36 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
Pulau Romang dengan luas 281 km² digunakan sebagai lokasi tambang emas.
- Sulawesi
Pulau Wawonii dengan luas 705 km² digunakan sebagai lokasi tambang nikel.
- Kalimantan
Pulau Sebuku dengan luas 225 km² digunakan sebagai lokasi tambang bijih besi.
Kerentanan Geospasial Pulau Kecil
Pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km², terutama yang jauh lebih mungil, seperti Gag dan Kawe, memiliki kerentanan geospasial yang sangat tinggi dan kompleks. Secara struktural, pulau kecil tak hanya sempit secara geografis, tetapi juga rapuh secara ekologis dan sosial. Ketika aktivitas ekstraksi skala besar seperti tambang nikel masuk tanpa kendali, dampaknya menjadi brutal, langsung, dan sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk dipulihkan.
Seperti dilaporkan oleh Associated Press, kerusakan akibat tambang di pulau kecil dapat memicu bencana yang menyebar cepat, dari tanah longsor yang menggusur habitat hingga sedimentasi berat yang mengubah warna laut menjadi cokelat keruh. Tidak ada cukup ruang alami untuk memulihkan luka ekologis.
Pulau Kawe, misalnya, secara tragis diperkirakan bisa lenyap dari peta dalam waktu 15 tahun jika tambang nikel terus dijalankan tanpa henti. Tanpa intervensi kuat, abrasi dan sedimentasi akan terus menggerogoti garis pantainya. Bandingkan dengan pulau besar yang memiliki waktu pemulihan jauh lebih panjang, bahkan bisa sampai ratusan tahun untuk memulihkan erosi tanah dan kehancuran hutan akibat tambang. Pulau kecil tak punya kemewahan waktu itu.
Lebih jauh lagi, dampak langsung dari tambang nikel terlihat di Pulau Manuran. Di sana, kolam pengendapan (settling pond) yang dibangun untuk menampung limbah tambang justru jebol secara tragis. Lumpur pekat beracun mengalir deras ke laut, membuat air pantai menjadi keruh dan mematikan biota laut di sekitarnya. Terumbu karang, yang sejatinya tumbuh perlahan dalam dekade atau abad, dalam sekejap kehilangan warna dan nyawa.
Catatan Penting dari Berbagai Pihak
Greenpeace mencatat dengan prihatin bahwa penambangan yang berlangsung di Gag, Kawe, dan Manuran telah menghapus lebih dari 500 hektare hutan tropis. Hal ini bukan sekadar angka, melainkan hilangnya ekosistem, seperti pohon-pohon penopang kelembaban tanah, rumah bagi burung-burung langka, dan penyangga kehidupan lokal, yang telah dihancurkan tanpa belas kasih.
Di dalam ekosistem sekecil itu, kehilangan satu spesies endemik bukan hanya kehilangan keanekaragaman, tetapi bisa berarti kepunahan lokal. Keterbatasan ruang dan habitat menyebabkan tak adanya tempat lain bagi spesies tersebut untuk pindah atau bertahan. Hal ini menjadikan setiap spesies di pulau kecil sebagai satu-satunya benteng keberadaannya. Jika rusak, hilanglah ia untuk selamanya.
Sementara itu, sedimentasi dari aktivitas tambang menyebar ke laut dengan sangat cepat, merusak terumbu karang bahkan tanpa menyentuhnya langsung. Bahan tambang yang terbawa arus mengendap di atas karang, menutup cahaya, dan menyebabkan coral bleaching yang menyedihkan. Dengan biodiversitas laut yang sedemikian kaya, kerusakan ini setara dengan menghancurkan laboratorium alam yang belum sempat diteliti.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperingatkan keras bahwa kerusakan akibat tambang di Raja Ampat tidak bisa dianggap sebagai isu lokal semata. Deforestasi yang brutal memicu pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, memperburuk krisis iklim global. Tindakan ini adalah kejahatan ekologis yang merambat diam-diam, tetapi sangat destruktif. Lebih dari itu, hilangnya terumbu karang dan sumber ikan tidak hanya mengancam keberlanjutan pangan lokal, tetapi juga merobek nilai-nilai budaya masyarakat adat yang hidup harmonis dengan alam.
Dalam konteks hukum, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik-praktik penambangan yang dilakukan di luar penataan ruang dan zonasi yang tepat dapat menimbulkan konflik ruang dan kewenangan. Hal ini mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28H UUD 1945. Penambangan yang dijalankan secara serampangan, apalagi tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat, adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang nyata.
Dalam kondisi serentan ini, eksploitasi pulau kecil bukan hanya salah secara teknis, melainkan juga keliru secara moral dan berbahaya secara jangka panjang. Kita sedang mempertaruhkan lebih dari sekadar daratan, kita tengah mempertaruhkan kehidupan.
Mari Berpikir untuk Masa Depan
Eksploitasi pulau kecil bukan urusan tata kelola lingkungan atau prosedur izin tambang belaka, melainkan soal keberlanjutan hidup di ruang yang sangat terbatas dan rentan. Pulau-pulau dengan luas di bawah 2.000 km² menyimpan ekosistem yang unik dan tidak tergantikan, di mana satu kesalahan dalam bentuk pembukaan lahan tambang, pencemaran air, atau deforestasi dapat memicu reaksi berantai, seperti tanah longsor, rusaknya jalur air, hingga hilangnya spesies endemik.
Dalam ruang sekecil itu, tak ada zona penyangga bagi alam untuk menyembuhkan diri. Dampak ekologis langsung akan memukul masyarakat adat yang bergantung sepenuhnya pada laut dan hutan sekitar untuk pangan, budaya, dan spiritualitas mereka.
Sebetulnya, landasan hukum di Indonesia sudah jelas. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit melarang segala bentuk penambangan di pulau kecil, termasuk pasir, minyak, gas, dan mineral. Aturan ini bukan sekadar norma administratif, tetapi perintah perlindungan ekologis yang wajib ditaati.
Namun, kenyataannya, banyak izin tambang tetap diterbitkan oleh pemerintah pusat hingga daerah, yang sering kali melanggar penataan ruang dan mengabaikan keberatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya ada di tingkat nasional, tetapi juga melekat di tingkat provinsi, kabupaten, hingga pemerintahan desa. Penegakan hukum dan kebijakan lingkungan di wilayah kepulauan harus dilakukan secara tegas, terkoordinasi, dan tanpa kompromi karena yang dipertaruhkan adalah masa depan ekologi Indonesia yang paling rentan.
Sumber: X @perupadata, The Associated Press, Tempo 1, Reuters, Media Indonesia, Tempo 2