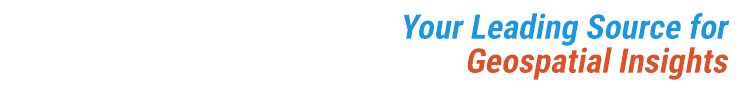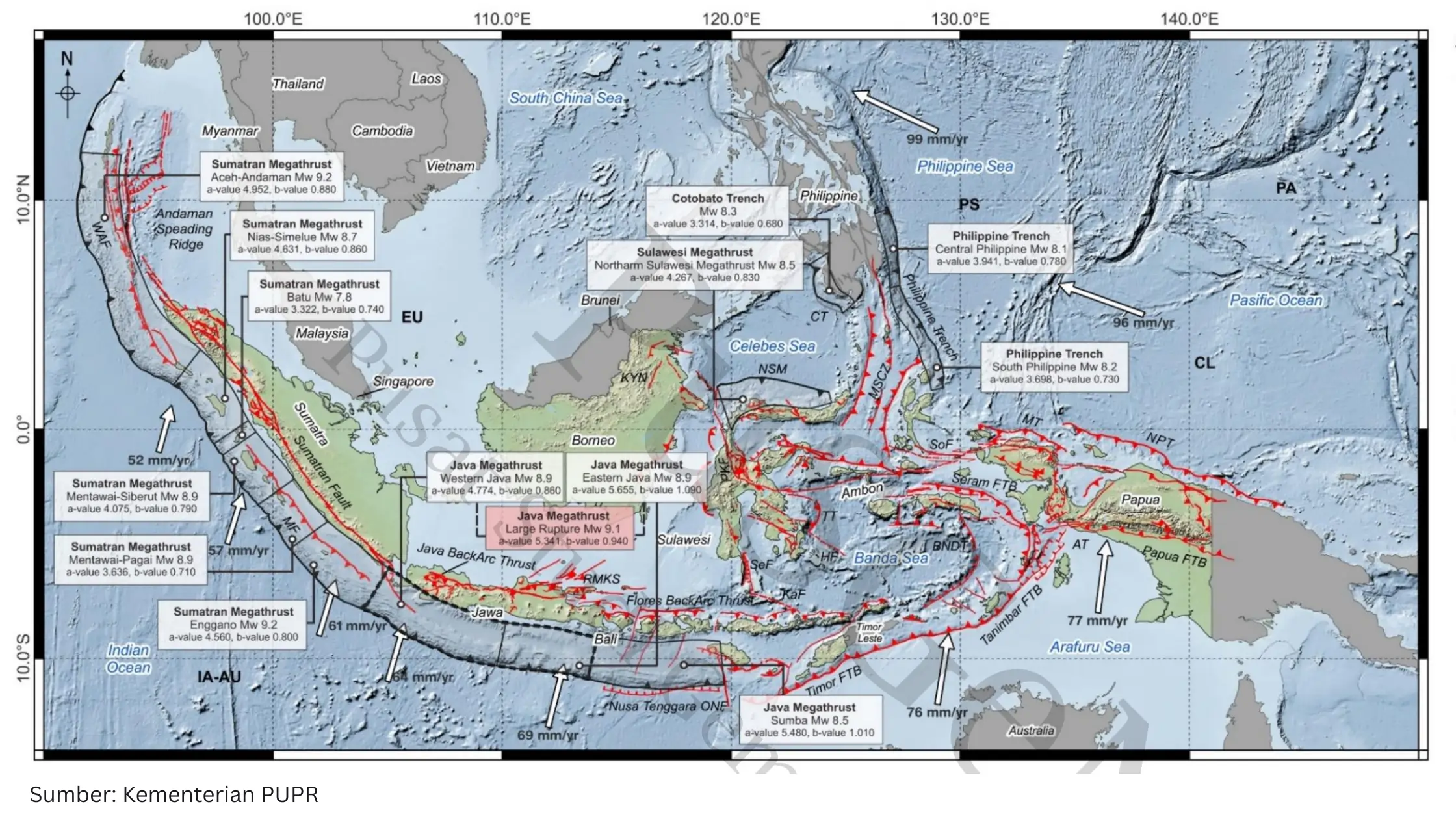Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dalam sejarah modern, di mana persoalan identitas, kedaulatan, dan perebutan wilayah terus menjadi sumber ketegangan. Selama puluhan tahun, berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, tetapi perdamaian yang berkelanjutan belum juga tercapai. Dalam konteks ini, solusi dua negara atau two-state solution sering dipandang sebagai opsi paling realistis untuk mengakhiri konflik panjang tersebut.
Pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara. Menurutnya, perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak Palestina diakui secara penuh, sementara keamanan Israel tetap dijamin oleh komunitas internasional. Sikap ini menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus menunjukkan upaya diplomasi yang seimbang: mendukung kemerdekaan Palestina tanpa mengabaikan stabilitas regional.
Namun, bila dilihat dari sudut pandang geospasial, tantangannya jauh lebih rumit. Konflik ini tidak hanya berkisar pada politik, tetapi juga menyangkut pengelolaan ruang dan wilayah. Perbatasan yang disengketakan, akses air, hingga fragmentasi wilayah Palestina menjadi hambatan nyata. Jalur Gaza yang terisolasi, permukiman Israel di Tepi Barat, dan status Yerusalem yang belum terselesaikan memperlihatkan betapa sulitnya membangun dua negara yang adil dan berdaulat.
Melalui kacamata geospasial, perdamaian bukan sekadar perjanjian diplomatik, melainkan rekonstruksi ruang hidup yang memungkinkan kedua bangsa hidup berdampingan. Pemetaan ulang wilayah, pembagian sumber daya yang adil, serta integrasi akses antarwilayah menjadi kunci menuju solusi berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kesepakatan politik dapat berjalan tanpa keadilan dalam tata ruang?
Tarik Ulur Two-State Solution Palestina-Israel
Two-state solution sendiri bukanlah gagasan baru bagi kedua negara yang terlibat dalam konflik. Konsep ini menyerukan pembentukan dua entitas berdaulat, Palestina dan Israel, dengan wilayah Palestina berada di sebelah barat Sungai Yordan. Namun, implementasi solusi tersebut selalu menghadapi jalan buntu karena persoalan perbatasan. Palestina bersama negara-negara Arab mendesak agar garis batas 1967 dijadikan acuan, sementara Israel menolak dengan alasan keamanan dan klaim historis atas wilayah tertentu. Kompleksitas tarik ulur batas ini tercermin dari rentetan sejarah diplomasi, mulai dari Resolusi PBB tahun 1974, Perjanjian Oslo 1993, hingga Konferensi Annapolis 2007. Semua upaya tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bukan sekadar politik identitas, melainkan juga perebutan ruang hidup yang memiliki nilai strategis, ekonomi, sekaligus simbolis.
Sayangnya, sejauh ini kedua pihak belum mendapatkan titik temu yang bisa diterima bersama. Berbagai resolusi dan prakarsa perdamaian yang ditawarkan sering kali gagal karena faktor kepercayaan, distribusi wilayah, hingga keterlibatan kekuatan internasional yang memiliki kepentingan berbeda. Palestina menuntut pengakuan kedaulatan penuh atas wilayah yang terfragmentasi, sementara Israel terus memperluas permukiman yang justru menambah ketegangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tarik ulur solusi dua negara tidak hanya terhambat oleh diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga oleh realitas spasial di lapangan yang makin sulit direkonsiliasi.
Garis Batas yang Tidak Pernah Jelas
Konflik Palestina-Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan masih menjadi salah satu isu geopolitik paling rumit di dunia. Salah satu sumber utama kebuntuan adalah persoalan garis batas atau garis demarkasi. Garis batas tahun 1967 kerap dijadikan acuan oleh PBB sebagai dasar solusi dua negara. Bagi Palestina, garis batas tahun 1967 adalah titik awal yang paling dasar (bukan tawaran maksimal) untuk mewujudkan negara merdeka. Namun, Israel memiliki pandangan berbeda dan terus melakukan perluasan wilayah. Akibatnya, dalam banyak perundingan, persoalan batas wilayah sering kali menjadi jalan buntu yang membuat negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan.
Sejarah konflik ini juga berkaitan erat dengan peristiwa Nakba pada 1948. Setelah mandat Inggris berakhir dan Israel mendeklarasikan kemerdekaan, lebih dari 700 ribu warga Palestina meninggalkan atau terpaksa meninggalkan tanah mereka. Banyak desa hancur, lahan beralih kepemilikan, dan sebagian besar dari mereka hingga kini hidup sebagai pengungsi. Sejak 1946, meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina turut memicu ketegangan yang berujung pada perubahan drastis peta wilayah. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam dinamika konflik yang masih terasa hingga sekarang.
Jika dilihat dari kacamata geospasial, kompleksitas konflik ini tampak lebih jelas. Lembah Yordan, wilayah strategis yang kaya sumber air, kini banyak berada di bawah kendali Israel. Sementara, Jalur Gaza menghadapi blokade dari berbagai sisi, yang membatasi pergerakan barang maupun penduduk. Di Tepi Barat, pembangunan permukiman membuat wilayah Palestina terfragmentasi menjadi kantong-kantong kecil yang sulit terhubung.
Dengan kondisi geografis seperti ini, mewujudkan solusi dua negara bukan hanya soal kesepakatan politik, melainkan juga membutuhkan penataan ulang tata ruang wilayah agar kedua masyarakat dapat hidup berdampingan secara adil dan berkelanjutan.
Menggagas Diplomasi Tata Ruang
Pidato Prabowo tentang keadilan bagi Palestina dan jaminan keamanan Israel hanya bisa diwujudkan jika ada penataan ruang yang adil. Pemetaan ulang perbatasan berbasis data spasial, pengelolaan bersama sumber daya air lintas batas, hingga kebijakan mobilitas antarwilayah bisa menjadi fondasi rekonsiliasi yang lebih konkret.
Analisis geospasial berperan penting dalam mengidentifikasi batas negara yang realistis, serta menunjukkan kemungkinan koeksistensi melalui distribusi ruang yang setara. Dengan kata lain, solusi politik perlu dipadukan dengan rekayasa tata ruang agar tidak berhenti pada teks perjanjian, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di lapangan.
Namun, konflik Palestina-Israel bukan sekadar perselisihan politik identitas, melainkan juga perebutan ruang hidup yang memiliki nilai strategis, ekonomi, sekaligus simbolis. Lembah Yordan, misalnya, bukan hanya lahan subur untuk pertanian, tetapi juga sumber air vital bagi kedua bangsa. Begitu pula dengan Yerusalem, yang memiliki makna spiritual dan historis mendalam, menjadikannya titik paling sensitif dalam perundingan. Tanpa tata kelola ruang yang adil, wilayah-wilayah strategis ini akan terus memicu ketegangan. Oleh karena itu, diplomasi tata ruang bisa menjadi pendekatan baru yang menjembatani kepentingan politik dengan kebutuhan praktis masyarakat dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih berkelanjutan.