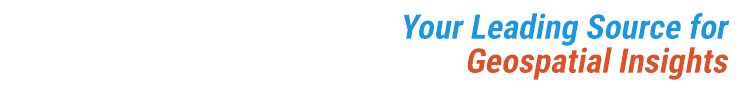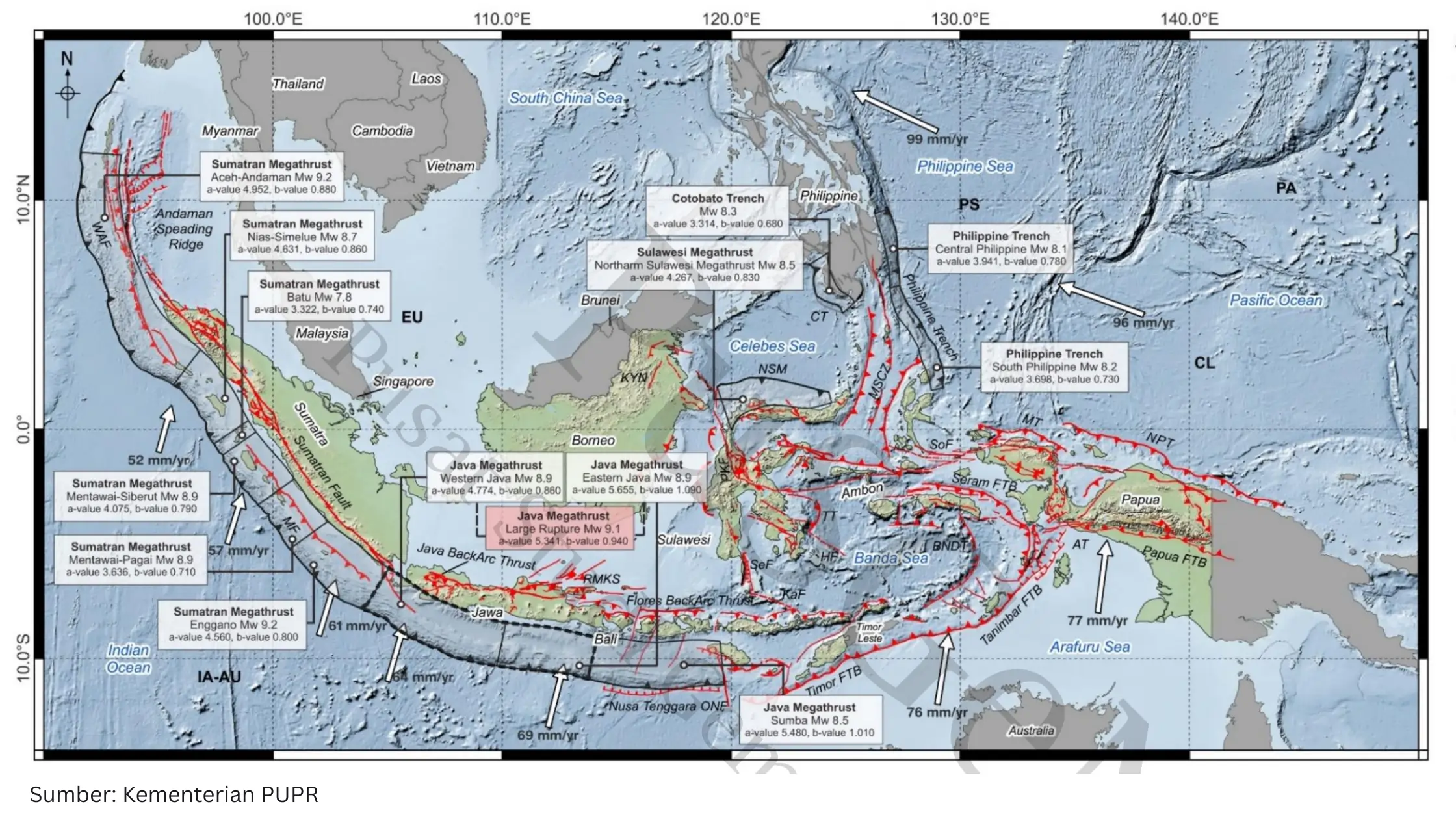Globalisasi telah menjadi salah satu istilah paling populer dalam wacana sosial, ekonomi, dan politik dunia sejak akhir abad ke-20. Ia digambarkan sebagai kekuatan besar yang meruntuhkan batas-batas negara, menciptakan integrasi ekonomi global, dan mempercepat pertukaran budaya lintas batas.
Namun, jika kita melihat dari perspektif spasial, tampak jelas bahwa globalisasi menyisakan ilusi keterhubungan yang tidak sepenuhnya merata. Di balik narasi dunia yang “semakin dekat”, terdapat realitas fragmentasi ruang, ketimpangan wilayah, dan marjinalisasi budaya lokal yang semakin menganga.
Dalam narasinya, globalisasi kerap digambarkan merevolusi cara manusia memaknai ruang dan waktu. Teknologi komunikasi digital memungkinkan informasi menyebar lintas benua dalam hitungan detik, dan transportasi modern memangkas jarak secara drastis. Konsep “ruang tanpa batas” (borderless space) ini menjadi ikon utama dari era ini, seolah-olah semua wilayah kini terkoneksi dan memiliki peluang yang setara.
Namun, anggapan ini lebih bersifat semu ketimbang nyata. Faktanya, tidak semua ruang memiliki akses yang sama terhadap jaringan global tersebut. Akses terhadap teknologi digital, infrastruktur logistik, dan pasar global sangat timpang, terutama antara pusat-pusat ekonomi dunia dan wilayah periferal. Di Indonesia, misalnya, konektivitas digital tinggi hanya terdapat di wilayah Jawa dan sebagian kota besar lainnya, sementara Papua dan sebagian besar wilayah timur Indonesia masih tertinggal secara infrastruktur digital maupun logistik.
Dengan kata lain, meskipun waktu bergerak lebih cepat secara global, tidak semua orang ikut bergerak di dalam kecepatan itu. Beberapa kelompok tertinggal, tersisih, dan kehilangan posisi dalam arus waktu global yang terus melaju.
Global Tapi Serasa Eksklusif
Ketimpangan spasial menjadi salah satu dampak paling nyata dari proses globalisasi. Alih-alih menyatukan wilayah secara harmonis, globalisasi justru mempertegas dikotomi antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran. Kawasan metropolitan berkembang pesat sebagai simbol dan pusat globalisasi, menjadi magnet bagi investasi, tenaga kerja, dan teknologi. Sementara itu, wilayah-wilayah pinggiran, kumuh, dan tertinggal semakin tergeser dari prioritas pembangunan.
Sebuah studi oleh Sugeng Setyadi, mencatat bahwa dalam konteks Asia Tenggara, kota-kota seperti Jakarta, Bangkok, dan Kuala Lumpur mengalami lonjakan ekonomi yang didorong oleh arus modal global. Namun, kota-kota kecil dan desa-desa di wilayah pinggiran mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran akibat tersisih dari jaringan global tersebut.
Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi global tak otomatis membawa pemerataan. Tanpa kebijakan spasial yang adil, pembangunan hanya akan berkonsentrasi pada ruang-ruang tertentu, menciptakan enclave modernitas di tengah lautan keterbelakangan.
Semua Dipaksa Seragam
Globalisasi juga memiliki dimensi kultural yang kerap direduksi menjadi gaya hidup kosmopolitan, seperti konsumsi produk global, bahasa Inggris sebagai bahasa utama, dan budaya Barat yang mendominasi media global. Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut sebagai homogenisasi budaya, di mana ekspresi lokal dan identitas tradisional mulai tergeser oleh budaya dominan global.
Ruang-ruang publik di kota-kota besar kini lebih menyerupai satu sama lain. Mal, kafe, toko dan supermarket waralaba, dan perumahan bergaya modern mendominasi, yang menghilangkan karakter lokal yang dulunya unik. Globalisasi, dalam hal ini, mempersempit ruang bagi ekspresi budaya lokal. Hal ini membuat, budaya seolah menjadi komoditas yang dikemas, dikontrol, dan didistribusikan oleh pasar global.
Namun, tak semua masyarakat menerima proses ini secara pasif. Di berbagai tempat, muncul gerakan resistensi budaya, baik dalam bentuk pelestarian tradisi, revitalisasi bahasa daerah, maupun penciptaan seni yang menggabungkan elemen lokal dan global secara kreatif.
Sebagai respons terhadap dominasi global tersebut, muncul pula strategi lokalisasi, yakni upaya untuk menyesuaikan proses globalisasi dengan nilai, norma, dan kebutuhan lokal. Lokalisasi ini tak hanya terjadi dalam budaya, tetapi juga dalam ekonomi dan kebijakan publik.
Contohnya, di Yogyakarta dan Bali, pemerintah daerah secara aktif menerapkan regulasi yang membatasi pembangunan retail modern dan menjaga eksistensi pasar tradisional serta UMKM lokal. Gerakan “cinta produk lokal” juga mulai menguat, tidak hanya sebagai strategi pemasaran, tapi juga sebagai pernyataan identitas dan kedaulatan ekonomi.
Fenomena lokalisasi ini menjadi penting karena menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak harus tunduk pada arus global secara total. Mereka dapat memilih, memilah, dan mengadaptasi apa yang masuk ke wilayahnya.
Pembangunan Berkembang, Alam yang Rusak Dimensi lain yang kerap dilupakan dalam wacana globalisasi adalah dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Perluasan industri global ke wilayah-wilayah baru sering kali dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan ruang-ruang komunitas lokal. Deforestasi, perampasan lahan, dan konflik agraria meningkat di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin seiring ekspansi investasi global di sektor perkebunan, tambang, dan infrastruktur.
Di sisi sosial, fragmentasi muncul dalam bentuk segregasi spasial, komunitas elite tinggal di kawasan eksklusif, sedangkan masyarakat marjinal terdorong ke pinggiran kota tanpa akses ke fasilitas dasar. Ketimpangan ini tak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga memicu konflik dan ketegangan antar kelompok.
Mulai Bertanya, Jangan Hanya Terbawa Arus
Globalisasi bukanlah sebuah proses yang netral dan menyeluruh, ia adalah proyek ekonomi-politik yang secara spasial sangat selektif, memperkuat beberapa wilayah sembari melemahkan wilayah yang lain. Dalam perspektif spasial, globalisasi menciptakan ilusi konektivitas yang sering kali menutupi fakta fragmentasi, eksklusivitas dan ketidakadilan.
Maka, penting bagi kita untuk terus mengembangkan perspektif kritis terhadap narasi globalisasi. Daripada sekadar menerima wacana dunia yang “semakin menyatu,” kita perlu bertanya “siapa yang disatukan, dan siapa yang ditinggalkan?” Dengan begitu, kita bisa merancang pembangunan yang lebih adil, berpihak pada lokalitas, dan menjadikan ruang sebagai arena perjuangan untuk kesetaraan.