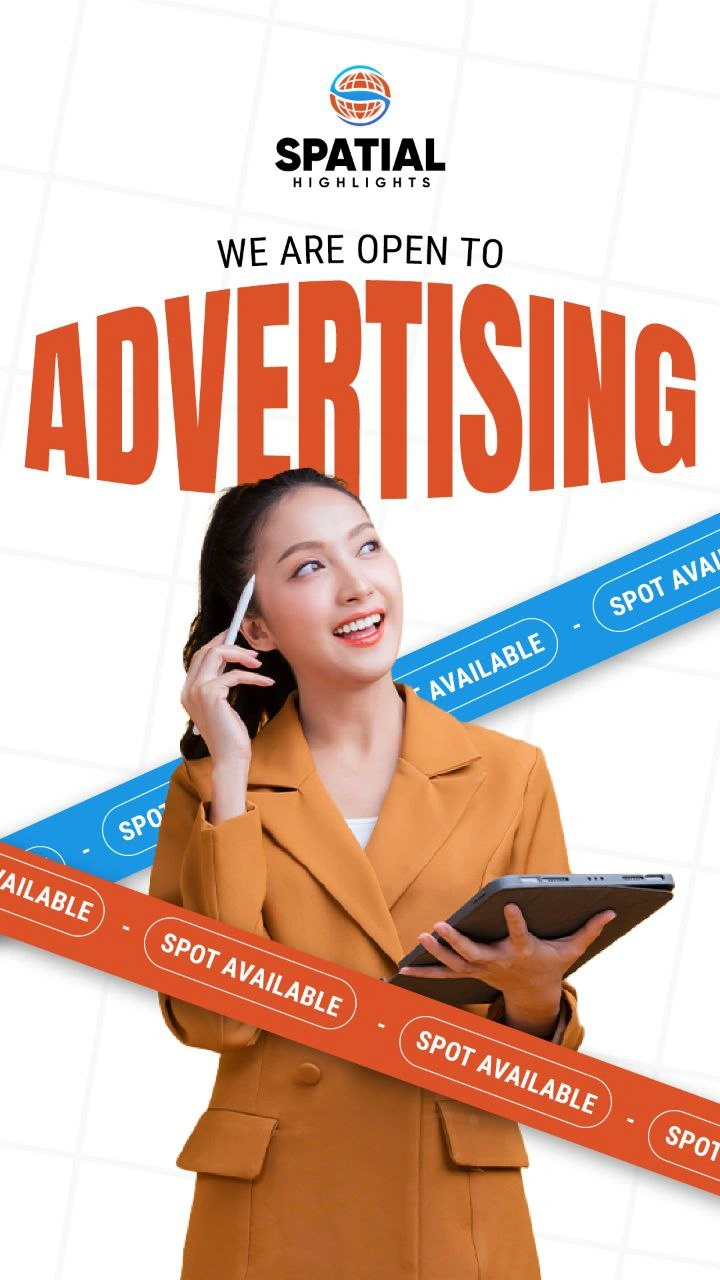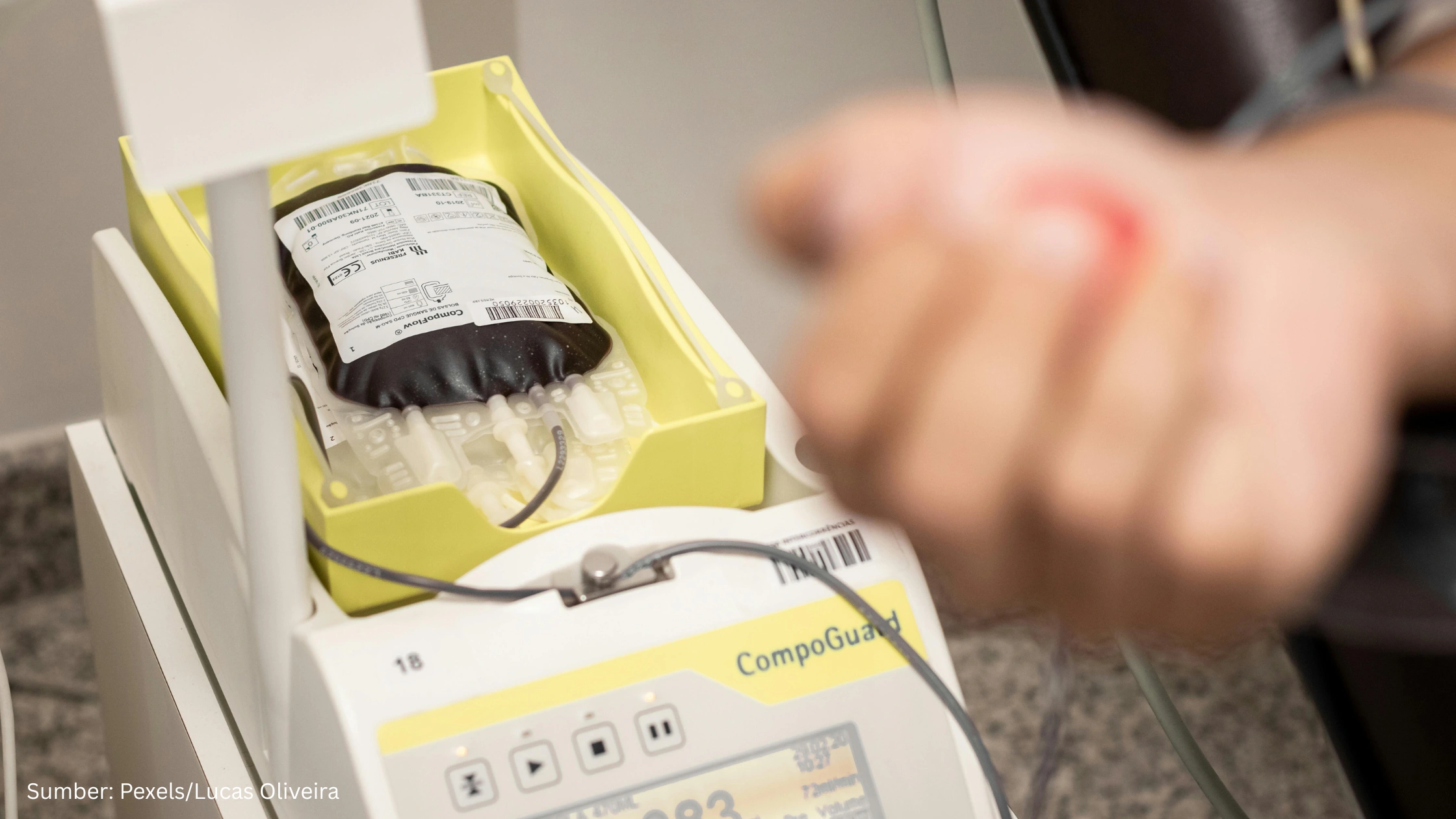BIG Diminta Tinjau Ulang Garis Batas antara Indonesia dan Timor Leste
Ketegangan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste kembali mencuat setelah masyarakat di Desa Inbate, Timor Tengah Utara, menilai adanya ketidakadilan dalam penetapan garis batas negara. Sengketa lahan yang hanya seluas belasan hektare itu ternyata menyimpan persoalan jauh lebih besar, bukan sekadar soal siapa yang berhak atas tanah, melainkan juga tentang identitas, kedaulatan, dan masa depan hubungan lintas batas. Guna menyikapi hal tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) didorong untuk meninjau ulang penetapan batas, guna memastikan keadilan spasial sekaligus mencegah konflik serupa di kemudian hari.
Secara geospasial, perbatasan darat Indonesia–Timor Leste membentang sepanjang ±253 kilometer, mencakup Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), hingga wilayah eksklave Oecusse di Timor Leste. Sejak Provisional Agreement 2005, titik-titik batas memang belum seluruhnya disepakati. Salah satu segmen paling rawan konflik adalah Naktuka di perbatasan Noel Besi–Citrana, yang hingga kini masih menyisakan area abu-abu, meski kesepakatan garis tengah telah dicapai pada 2019. Ketidakjelasan batas inilah yang kembali menimbulkan ketegangan di wilayah TTU, khususnya di Desa Inbate, tempat masyarakat mengklaim kehilangan lahan adat seluas 12,60 hektare yang kini masuk dalam peta wilayah Timor Leste.
Berdasarkan laporan Pos-Kupang.com, Bupati TTU Yoseph Falentinus Delasalle Kebo menegaskan bahwa masyarakat menuntut BIG untuk meninjau ulang garis batas tersebut. Dari perspektif geospasial, klaim ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan tanah dan penggunaan lahan pertanian, tetapi juga berpengaruh pada identitas sosial dan keberlangsungan kehidupan adat di sekitar dusun Nino, Desa Inbate.
Selain peninjauan batas, masyarakat juga menekankan pentingnya dialog adat lintas negara yang melibatkan 12 suku adat dari kedua belah pihak. Yoseph menyebut jalur adat ini sebagai pendekatan yang efektif mencegah konflik di masa depan. Sejarah membuktikan bahwa mekanisme budaya pernah berhasil meredakan sengketa di Naktuka dan Oepoli melalui mediasi tradisional bersama tokoh adat Oecusse. Hal ini menunjukkan bahwa garis batas negara bukan hanya persoalan teknis pemetaan, melainkan juga menyangkut relasi sosial dan kultural masyarakat perbatasan.
Di sisi lain, masyarakat menuntut agar pelaku penembakan dalam insiden terakhir diproses hukum oleh otoritas Timor Leste. Mereka juga meminta aparat perbatasan berasal dari warga lokal Oecusse yang menguasai bahasa Dawan, karena banyak kesalahpahaman dipicu oleh keterbatasan komunikasi lintas bahasa. Dengan demikian, aparat lokal dapat berfungsi sebagai peredam konflik sekaligus jembatan komunikasi.
Kajian ulang oleh BIG diharapkan tidak hanya mempertegas garis batas secara hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spasial, sosial, dan budaya. Dengan pendekatan itu, potensi konflik perbatasan bisa diredam sehingga tidak berulang sebagaimana pernah terjadi pada kasus Aceh–Sumut maupun sengketa 13 pulau di Jawa Timur.