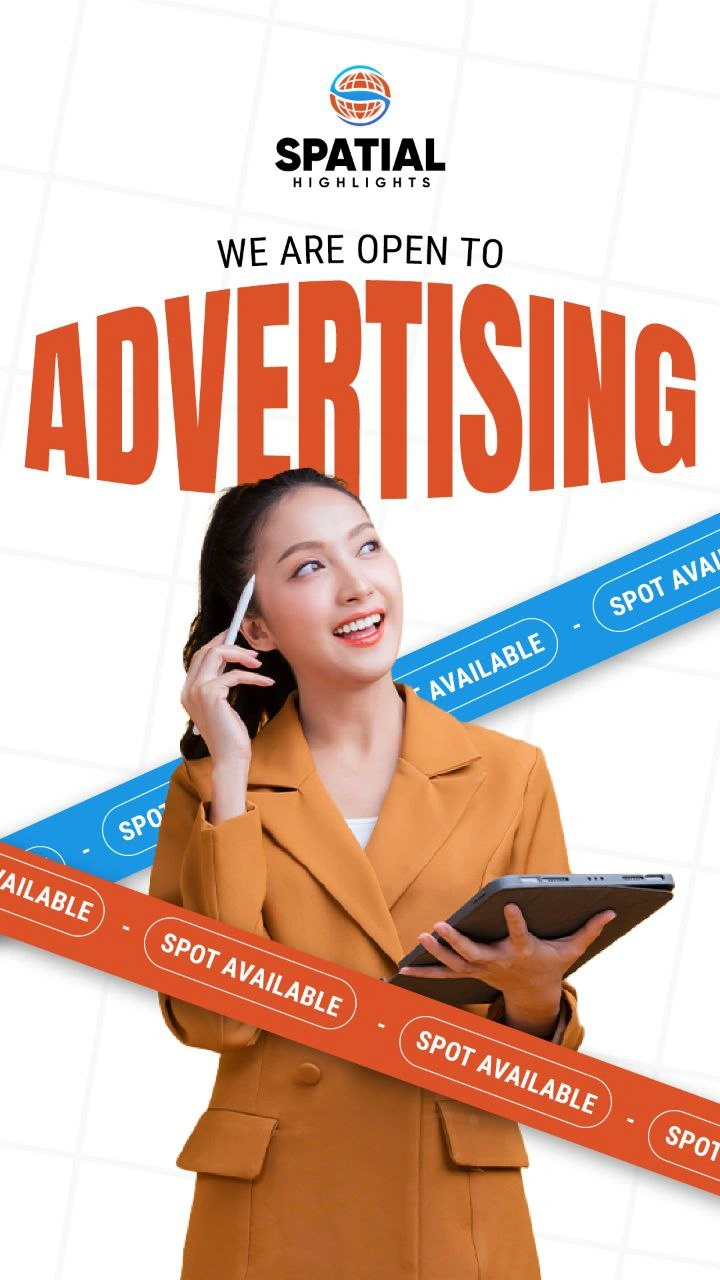3 Warisan Tata Ruang Zaman Kolonialisme yang Membentuk Ruang Publik Indonesia di Era Modern
Penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad tidak hanya meninggalkan warisan berupa kekuasaan politik dan sistem ekonomi kolonial, tetapi juga membentuk fondasi tata ruang kota-kota di Indonesia hingga saat ini. Kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, mengadopsi pola tata kota yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan kolonial, bukan masyarakat lokal.
Perencanaan ruang yang dilakukan Belanda mencerminkan strategi penguasaan teritorial, kontrol sosial, serta efisiensi ekonomi kolonial. Lalu, bagaimanakah tata ruang kolonial terbentuk? Apakah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan bagaimana warisan tersebut masih terasa dalam ruang-ruang urban Indonesia masa kini?
- Segregasi Spasial Berdasarkan Ras dan Kelas Sosial
Salah satu ciri dominan dalam tata kota kolonial adalah adanya segregasi spasial berdasarkan ras dan kelas sosial. Pemerintah kolonial secara sistematis memisahkan kawasan permukiman antara warga Eropa, Tionghoa, Arab, dan pribumi. Wilayah Eropa biasanya terletak di pusat kota dengan akses infrastruktur terbaik, seperti jalan lebar, taman, rumah besar, dan saluran air bersih.
Sebaliknya, wilayah pribumi sering kali terpinggirkan secara geografis dan infrastruktur. Hal ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat hierarki kekuasaan dalam ruang. Tak heran jika di era modern ini, di kota-kota besar di Indonesia masih dijumpai kampung-kampung etnis, seperti Kampung Arab ataupun daerah Pecinan.
Hal ini bermula dari Batavia, atau yang kini dikenal sebagai Jakarta, yang merupakan pusat awal eksperimen tata kota kolonial Belanda yang didirikan VOC pada 1619. Dibangun sebagai kota pelabuhan dan pusat administrasi, tata letaknya menyerupai kota-kota Eropa, khususnya Amsterdam, melalui pola grid, kanal-kanal, benteng, dan gudang penyimpanan barang ekspor.
Namun, desain yang tidak sesuai dengan kondisi tropis Indonesia membuat kanal-kanal justru menjadi sarang penyakit akibat sanitasi buruk dan kelembapan tinggi sehingga angka kematian akibat malaria dan disentri meningkat tajam. Akibatnya, pemerintah kolonial memindahkan pusat administrasi ke daerah yang lebih tinggi dan dianggap lebih sehat, yakni Weltevreden (kini kawasan Gambir), yang sekaligus menandai awal pemisahan antara pusat komersial dan administratif, sebuah warisan tata ruang yang masih tercermin era modern.

- Infrastruktur sebagai Alat Kontrol
Belanda memanfaatkan pembangunan infrastruktur sebagai alat strategis untuk memperkuat kontrol atas wilayah jajahan. Salah satu proyek besar adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang membentang dari Anyer hingga Panarukan sejauh lebih dari 1.000 km. Dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19, jalan ini tidak hanya mempercepat mobilitas militer dan logistik kolonial, tetapi juga membuka wilayah-wilayah baru untuk eksploitasi hasil bumi.
Di sisi lain, pembangunan jaringan rel kereta api oleh pemerintah kolonial juga mengikuti logika penguasaan. Konsep "benteng stelsel" diterapkan, di mana stasiun dan jalur kereta dibangun dengan jarak tertentu untuk memudahkan pengawasan serta mempercepat respons terhadap pemberontakan, terutama dari basis-basis perlawanan masyarakat Islam dan santri di pedalaman
Contoh di era modern yang mencerminkan logika serupa dapat dilihat pada pembangunan infrastruktur strategis oleh pemerintah Indonesia, seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Jalan Tol Trans-Jawa yang membentang lebih dari 1.000 km bukan hanya mempercepat arus logistik dan mobilitas masyarakat, melainkan juga menghubungkan sentra-sentra produksi ke pasar nasional maupun global, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi.
Sementara itu, Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menjadi bagian dari visi konektivitas nasional dalam proyek Global Maritime Fulcrum dan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Selain untuk memacu pertumbuhan kawasan metropolitan baru, seperti Rebana dan Walini, proyek tersebut juga memiliki dimensi strategis, yaitu mempertebal kontrol negara atas jalur vital antara Jakarta dan Jawa Barat.
Dengan demikian, meski dalam konteks yang berbeda, pembangunan infrastruktur modern tetap berfungsi ganda. Fungsi pertama adalah sebagai motor ekonomi, dan fungsi lainnya sebagai instrumen geopolitik dan geostrategis, sebagaimana Jalan Raya Pos dan jaringan rel kereta di masa kolonial.

- Tata Ruang Hierarkis yang Dorong Urbanisasi
Tata ruang kolonial membentuk struktur sosial kota yang sangat hierarkis dan masih terasa hingga era modern. Kebijakan seperti sistem tanam paksa (cultuurstelsel) tidak hanya menguras sumber daya manusia dan alam, tetapi juga memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah kota tertentu. Tak heran urbanisasi terjadi secara besar-besaran, terutama setelah munculnya industri perkebunan dan tambang, yang memaksa masyarakat desa berpindah ke kota untuk bekerja sebagai buruh dan mendorong peningkatan kebutuhan hunian.
Sayangnya, ketimpangan yang diwariskan tersebut menciptakan fenomena urban sprawl, yang terlihat dari perbedaan mencolok antara sebaran penduduk pusat kota dengan kawasan kumuh yang terus berkembang di pinggiran. Contoh paling nyata dapat dilihat pada perkembangan Jakarta, di mana pusat kota seperti Sudirman–Thamrin dan Kuningan tumbuh menjadi kawasan bisnis elit dengan gedung pencakar langit, sementara kelas pekerja yang tidak mampu menanggung biaya hidup tinggi terdorong untuk tinggal di Bekasi, Depok, atau Tangerang.
Pola serupa juga muncul di kota industri, seperti Medan atau Surabaya, di mana kawasan industri besar memusat di satu wilayah, sementara permukiman buruh tumbuh secara sporadis tanpa perencanaan matang di pinggiran. Dengan demikian, tata ruang kolonial yang hierarkis terus berevolusi dan meninggalkan jejak dalam bentuk segregasi sosial-ekonomi serta ketimpangan pembangunan kota modern di Indonesia.
Baca juga: Segregasi Spasial: Ketika Ruang Ikut Menciptakan Kesenjangan
Masa Lalu yang Menghantui Masa Kini
Warisan tata ruang kolonial bukan sekadar catatan sejarah, tetapi realitas yang masih membentuk wajah kota-kota Indonesia hingga kini. Pola hierarkis, ketimpangan akses, dan orientasi pembangunan yang berakar dari kepentingan kolonial terbukti menimbulkan tantangan serius dalam tata kelola kota modern, mulai dari urban sprawl, kemacetan, hingga kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam.
Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak sekadar mewarisi, tetapi juga merevisi dan menyesuaikan tata ruang kota agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan begitu, kota-kota di Indonesia tidak lagi hanya menjadi cermin masa lalu yang menghantui, melainkan ruang hidup yang memberi harapan bagi masa depan.