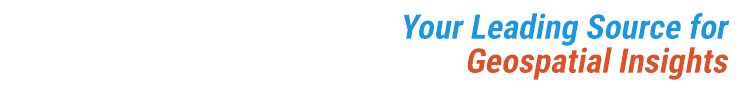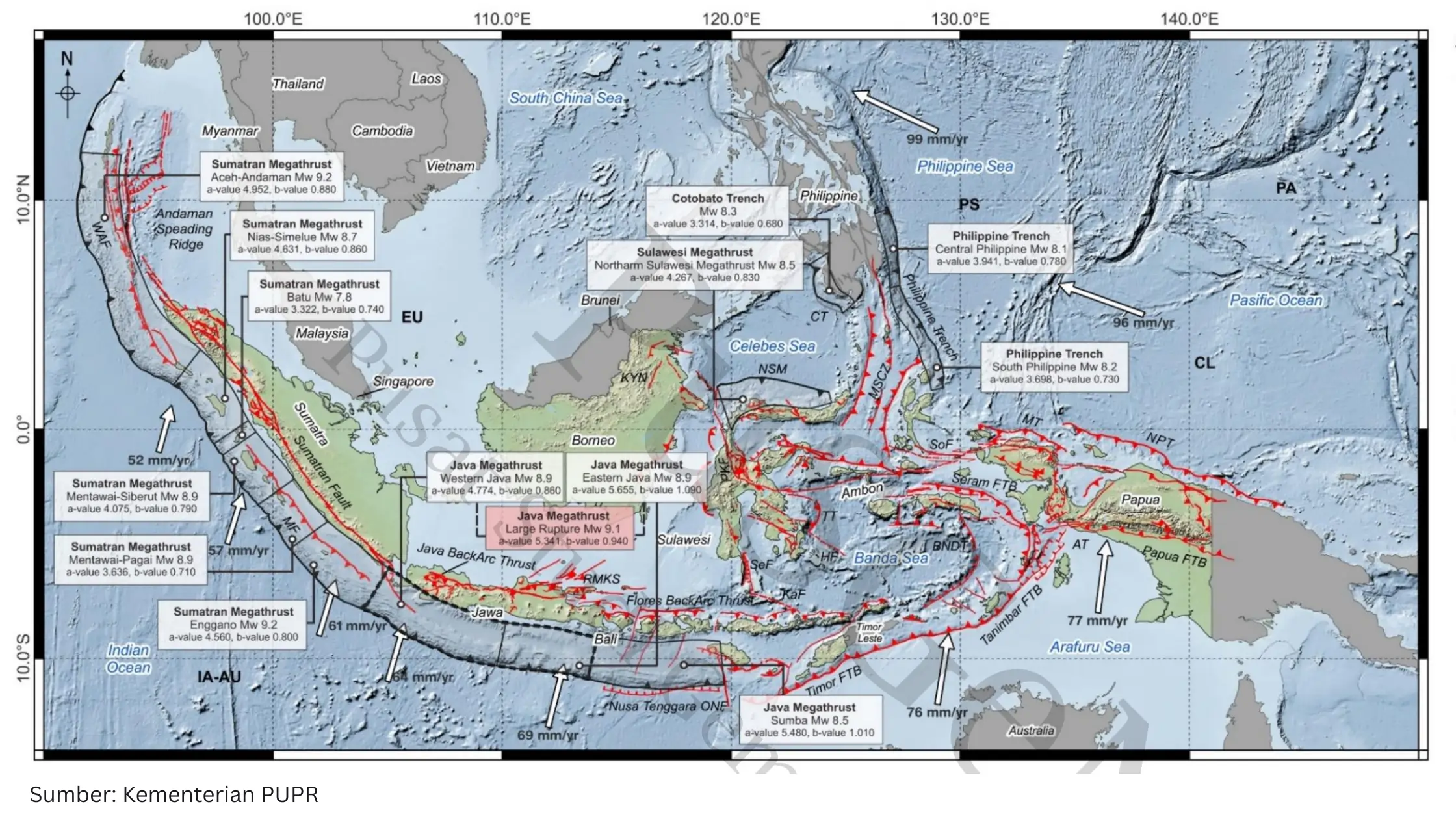Jika kamu pernah menyusuri Jalan Raya Seturan di Kabupaten Sleman, ada hal mencolok yang tak bisa diabaikan, yaitu deretan kafe atau coffee shop yang menghiasi sisi kiri dan kanan jalan. Dalam bentangan sepanjang 1,5 kilometer, setidaknya terdapat sekitar 25 kafe yang berdiri berdempetan, dengan jarak antarkafe rata-rata sekitar 60 meter. Artinya, dalam satu menit berjalan kaki, seseorang bisa menemukan lebih dari satu pilihan tempat untuk menyeruput secangkir kopi. Begitu pula di Jalan Babarsari, yang bahkan memiliki kepadatan lebih tinggi, satu kafe setiap 57 meter.
Dalam cakupan area seluas sekitar 18,5 km², tercatat terdapat kurang lebih 271 kafe yang tersebar di empat kelurahan, Seturan, Condongcatur, Babarsari, dan Depok. Artinya, ada 14,7 kafe dalam setiap kilometer persegi, sebuah tingkat kepadatan yang lebih menyerupai pusat komersial ketimbang kawasan hunian. Angka ini menunjukkan betapa kuatnya penetrasi bisnis gaya hidup, khususnya sektor kopi, dalam ekosistem ruang kota yang awalnya didesain untuk kebutuhan domestik.
Fenomena ini tak berdiri sendiri. Seturan dan Babarsari merupakan bagian dari kawasan urban yang dihuni ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sekitarnya. Tak heran, wilayah ini kerap dijuluki sebagai “SCBD”-nya Yogyakarta, akronim dari nama keempat kelurahan tersebut. Simpelnya, wilayah tersebut mirip pusat bisnis dan hiburan di Jakarta, namun dalam versi kampus dan kos-kosan.
Ruang Baru Interaksi Sosial
Keberadaan coffee shop tidak lagi terikat pada pusat-pusat administrasi atau industri, melainkan pada titik-titik pertemuan antara mobilitas penduduk muda, budaya populer, dan digitalisasi gaya hidup. Sementara itu, kota bukan hanya menjadi tempat tinggal, melainkan juga tempat untuk nongkrong, membuat konten, dan menampilkan identitas gaya hidup.
Dalam teori sosiologi urban kontemporer, konsep third place atau ruang ketiga yang dikemukakan oleh Ray Oldenburg menjadi kunci untuk memahami fenomena sosial yang muncul selain di rumah (ruang pertama) dan tempat kerja atau pendidikan (ruang kedua). Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, coffee shop, terutama di kota pelajar, seperti Yogyakarta, telah menjelma menjadi bentuk nyata dari ruang ketiga tersebut. Ruang ketiga sendiri adalah tempat di mana orang dapat bersantai, berinteraksi, dan menikmati kebersamaan tanpa tekanan atau kewajiban yang terkait dengan rumah atau pekerjaan.
Kenyamanan fisik dalam coffee shop: Wi-Fi gratis, colokan listrik, pencahayaan remang, serta suasana akustik yang dirancang untuk menenangkan, sering kali menjadi alasan utama popularitasnya di kalangan mahasiswa. Beberapa kafe bahkan menginisiasi kegiatan rutin seperti kelas terbuka, mini talks, atau malam puisi yang mengundang partisipasi publik. Dengan demikian, coffee shop memainkan peran sebagai katalis terbentuknya micro-community antarindividu dari berbagai latar belakang mahasiswa, pekerja lepas, pegiat seni, hingga pemilik bisnis rintisan. Di ruang ini, batas antara aktivitas santai dan kerja produktif menjadi cair, bahkan menyatu.
Konsekuensi Sosial dari Ruang Kota yang Tersusun Ulang
Fenomena ini turut berkontribusi pada pembentukan lanskap kota yang baru. Coffee shop tidak hanya menempati lahan kosong atau ruko tak terpakai, tetapi sering menggantikan fungsi ruang hunian menjadi area komersial. Di beberapa titik, rumah warga disulap menjadi kafe estetik. Dengan demikian, fungsi sosial ruang permukiman bergeser menjadi ruang konsumerisme. Hal ini mempercepat proses gentrifikasi mikro, khususnya di sekitar kampus-kampus, seperti UGM, UIN, dan STIE YKPN.
Dalam konteks ini, coffee shop bukan sekadar representasi tren gaya hidup, tetapi juga aktor dalam pergeseran tata ruang urban. Pemetaan distribusi coffee shop yang beririsan dengan sebaran hunian mahasiswa akan memperlihatkan tekanan spasial terhadap permukiman.
Analisis geospasial berbasis data persebaran kafe, densitas penduduk, dan fluktuasi harga sewa akan membantu memahami bagaimana ruang kota mengalami restrukturisasi kultural. Dengan melihatnya secara kritis dan mendalam, kita bisa memahami bahwa coffee shop bukan sekadar tempat minum kopi, melainkan ruang sosial yang berperan penting dalam membentuk narasi kehidupan urban di Yogyakarta hari ini.