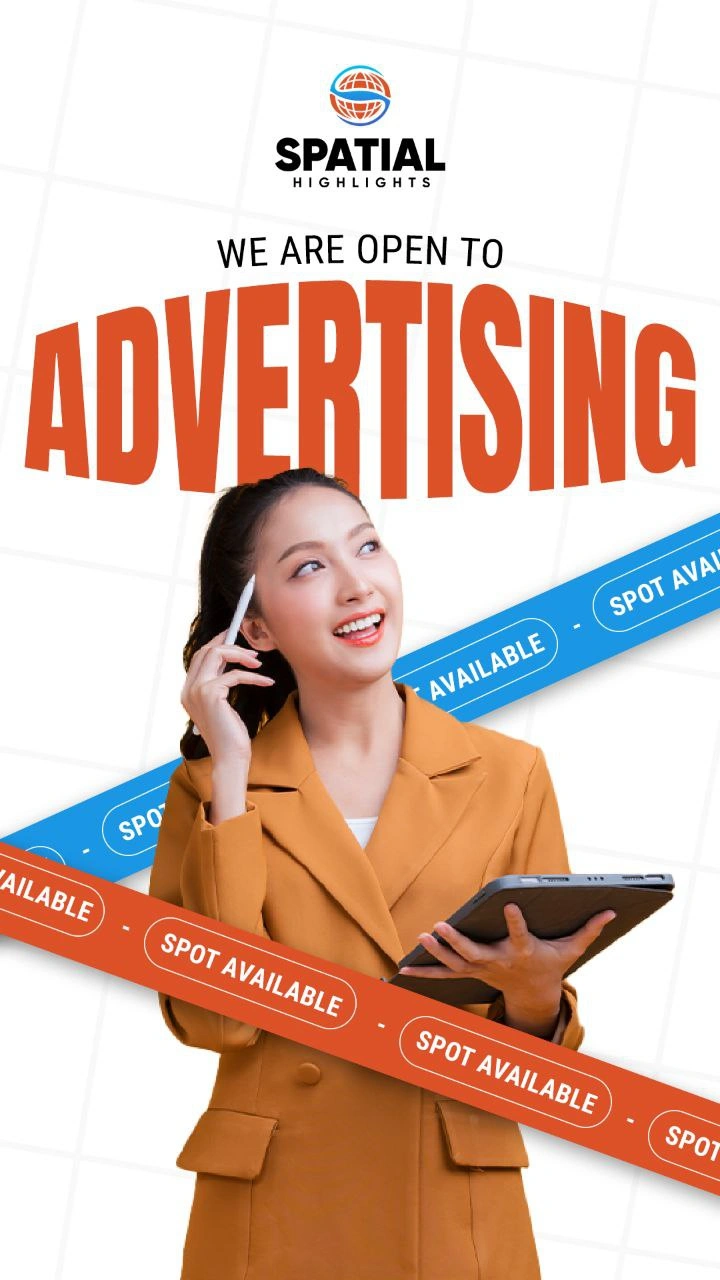Paparan Radiasi Tinggi, Apakah Cikande akan Menjadi Kota Mati seperti Chernobyl dan Fukushima?
Ketika berita tentang penolakan udang dan cengkih asal Indonesia oleh otoritas Amerika Serikat mencuat ke publik, banyak yang memandangnya sebagai persoalan ekspor semata. Namun, di balik larangan yang dikeluarkan oleh Food and Drug Administration (FDA) tersebut, tersembunyi persoalan yang jauh lebih kompleks, yaitu ancaman kontaminasi radioaktif yang dapat mencederai lingkungan dan kesehatan publik. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran teknis dalam rantai produksi pangan, melainkan juga potensi krisis ekologi yang perlu diselidiki secara ilmiah, terutama melalui pendekatan analisis geospasial.
Situasi menjadi makin mengkhawatirkan setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa sejumlah titik di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memiliki tingkat radiasi mencapai 875.000 kali lipat dari batas aman. Standar paparan radiasi yang dianggap aman di Indonesia adalah 0,11 mikrosievert per jam, tetapi di Cikande ditemukan paparan hingga 33.000 mikrosievert per jam.
Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 32 titik terkontaminasi zat radioaktif yang diduga berasal dari aktivitas peleburan limbah baja dan besi. Untuk mencegah risiko lebih besar, kawasan tersebut kini diberi tanda bahaya. Kemudian, akses masyarakat juga dibatasi dan 1.600 pekerja industri menjalani tes kesehatan untuk memastikan keselamatan mereka.
Namun, di tengah temuan radiasi ekstrem di Cikande dan kasus kontaminasi pada produk ekspor, muncul pertanyaan mendasar: langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia untuk memastikan penanganan menyeluruh terhadap paparan radiasi ini, mulai dari pemetaan, pemulihan lingkungan, hingga pencegahan agar dampaknya tidak meluas dan memengaruhi aspek kehidupan lain?
Kronologi Paparan Radiasi di Cikande
Kasus paparan radioaktif yang mengguncang industri ekspor Indonesia bermula pada awal Agustus 2025, ketika FDA Amerika Serikat mendeteksi keberadaan radionuklida Cesium-137 (Cs-137) pada sampel udang beku asal Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada 19 Agustus 2025, FDA menyatakan bahwa produk tersebut berasal dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS). Cs-137 merupakan isotop radioaktif hasil fisi nuklir yang sangat berbahaya karena mampu bertahan lama di lingkungan dan menimbulkan dampak biologis jangka panjang meski dalam dosis rendah. FDA menegaskan bahwa konsumsi produk terpapar Cs-137 dapat memicu gangguan sistem saraf dan meningkatkan risiko kanker. Oleh karena itu, produk udang tersebut dilarang beredar dan direkomendasikan untuk tidak dikonsumsi masyarakat.
Tidak lama kemudian, kasus serupa menjerat PT Natural Java Spice (Natural Java). Dalam Import Alert 99-51 yang diterbitkan pada 18 September 2025, seluruh produk rempah-rempah perusahaan tersebut masuk ke Red List karena hasil penyaringan menunjukkan indikasi kontaminasi Cs-137. FDA menduga sumber kontaminasi berasal dari residu bahan radioaktif yang menetap di kawasan industri Indonesia. Laporan lembaga itu bahkan menyinggung bahwa kadar Cs-137 tinggi biasanya hanya ditemukan di lokasi pascakejadian besar, seperti Chernobyl (1986) dan Fukushima (2011). FDA kemudian meminta pemerintah Indonesia dan perusahaan terkait memberikan bukti penanganan yang memadai agar ekspor berikutnya memenuhi standar keamanan pangan.
Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran serius terhadap sumber radiasi domestik, terutama di kawasan industri yang padat, seperti Modern Cikande di Banten. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang ekspor yang ditolak, melainkan apakah paparan radiasi di Cikande berpotensi menciptakan “zona mati” seperti dua bencana nuklir paling terkenal dalam sejarah modern.
Bagaimana Nasib Cikande?
Ketika KLHK mengumumkan temuan radiasi hingga 33.000 mikrosievert per jam di Kawasan Industri Modern Cikande, publik langsung terkejut. Angka tersebut berarti 875.000 kali lebih tinggi dari batas aman untuk masyarakat umum, bahkan melampaui ambang paparan maksimal bagi petugas reaktor nuklir yang dibatasi hanya 50 milisievert per tahun. Dalam konteks ilmiah, tingkat radiasi setinggi itu bukan sekadar penyimpangan biasa, melainkan sinyal adanya sumber radioaktif atau limbah berbahaya yang tersebar di area terbuka. Jika kondisi ini dibiarkan, potensi dampaknya tidak hanya menyentuh kesehatan manusia melalui paparan langsung dan rantai makanan, tetapi juga mencemari tanah, air tanah, dan udara dalam radius yang luas.
Namun, apakah Cikande benar-benar akan bernasib seperti Chernobyl di Ukraina atau Fukushima di Jepang? Secara skala, tentu berbeda. Di Chernobyl, tingkat radiasi ekstrem di sekitar reaktor yang meledak mencapai 300 hingga 500 sievert per jam, cukup untuk membunuh manusia dalam hitungan menit.
Sementara di Fukushima, paparan tertinggi di dalam area reaktor mencapai 400 milisievert per jam, dengan beberapa titik ekstrem hingga 1.000 milisievert per jam. Di permukiman sekitar Fukushima, radiasi berkisar antara 0,5–5 milisievert per jam. Jika dibandingkan, tingkat radiasi di Cikande sebesar 33 milisievert per jam memang jauh lebih rendah daripada pusat bencana nuklir, tetapi setara dengan zona berbahaya di sekitar Fukushima atau wilayah eksklusi luar Chernobyl beberapa hari setelah kecelakaan.
Dari sudut pandang analisis geospasial, situasi Cikande tetap harus dipandang serius. Jika Cs-137 yang terdeteksi menyebar melalui air tanah, udara, atau sistem drainase industri, dampaknya bisa meluas dan bertahan hingga puluhan tahun, meninggalkan jejak radioaktif yang sulit dipulihkan. Apabila tidak segera ditangani, masyarakat di sekitar kawasan industri berpotensi menghadapi dampak kesehatan jangka panjang, mulai dari peningkatan kasus gangguan pernapasan hingga risiko kanker akibat akumulasi paparan radiasi rendah.
Kota mati tidak selalu lahir dari ledakan besar, kadang tumbuh perlahan dari kelalaian manusia dalam mengawasi lingkungannya sendiri. Dengan begitu, pertanyaan terpenting bukan lagi “Apakah Cikande akan menjadi kota mati?”, melainkan “Apakah kita akan membiarkannya menuju ke arah itu tanpa bertindak cepat?”
Belajar dari Chernobyl dan Fukushima
Tragedi Chernobyl dan Fukushima memberi pelajaran bahwa bencana radiasi tidak berhenti pada ledakan awal, melainkan berlanjut sebagai krisis lingkungan jangka panjang. Dari sudut pandang geospasial, kedua wilayah tersebut menata kembali mitigasinya melalui strategi exclusion zone mapping, yaitu pemetaan tingkat radiasi berdasarkan radius paparan, arah angin dominan, serta pola sebaran air tanah dan vegetasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menentukan zona berbahaya, membatasi aktivitas manusia, dan merancang jalur evakuasi serta pembersihan wilayah secara efisien.
Dalam konteks Indonesia, Cikande dapat belajar dari model tersebut dengan menerapkan sistem pemetaan risiko lingkungan berbasis sensor radiasi dan data spasial real-time sehingga potensi kontaminasi dapat dideteksi lebih dini sebelum meluas ke area permukiman atau sumber pangan. Pendekatan geospasial juga dapat memantau pergerakan Cs-137 melalui simulasi aliran air dan udara untuk memberikan dasar ilmiah bagi tindakan mitigasi yang presisi dan terukur.
Lebih jauh, teknologi geospasial dapat menjadi jembatan antara sains lingkungan dan kebijakan publik. Pemerintah daerah dapat memetakan area risiko tinggi, mengawasi pembuangan limbah industri, serta mengintegrasikan pemantauan radiasi ke dalam sistem perizinan kawasan industri. Dengan cara ini, pengawasan berbasis data spasial tidak hanya menjadi respons terhadap larangan ekspor, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keselamatan lingkungan nasional.
Kasus radiasi pada udang dan cengkih asal Indonesia adalah peringatan keras bagi kawasan industri seperti Cikande. Dengan belajar dari pengalaman Chernobyl dan Fukushima, Cikande memiliki kesempatan untuk memperkuat ketahanan ekologis dan reputasi industrinya melalui penerapan teknologi geospasial yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Masa depan Cikande tidak akan menjadi kota mati, asal pemerintah dan industri bertindak cepat, cermat, dan berbasis ilmu pengetahuan.